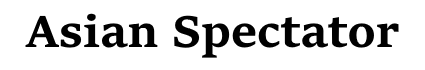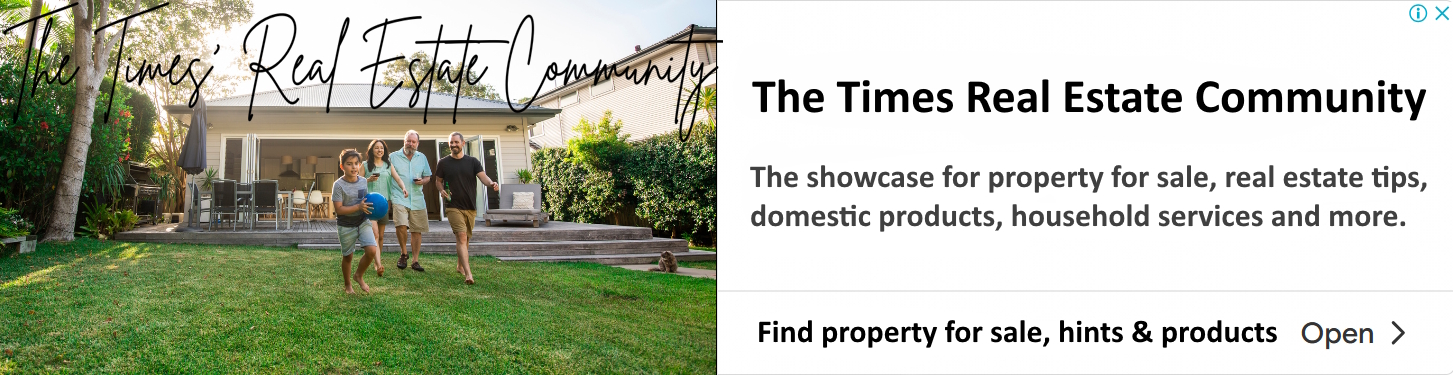Riset temukan 4 faktor penyebab melambungnya ongkos politik dalam pemilu
- Written by Ella Syafputri Prihatini, Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sudah jadi pemahaman umum bahwa ongkos berkompetisi dalam politik tidaklah sedikit. Biaya ini pun terus mengalami inflasi dari pemilu ke pemilu. Riset terbaru[1] kami menemukan bahwa calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 telah mengeluarkan budget yang fantastis, mencapai miliaran rupiah, dan terdistribusi dalam empat tahapan pemilu[2], yakni pencalonan, kampanye, pemilihan, dan pascapemilihan.
Responden dalam riset kami adalah para caleg yang mengikuti Pemilu 2024, mewakili partai besar dan partai kecil. Mereka mengakui bahwa biaya yang mereka keluarkan sangatlah besar. Rata-rata nominal yang mereka keluarkan mencapai Rp5 miliar, dengan angka paling sedikit berkisar Rp200 juta.
Angka aktual dari masing-masing caleg bisa jadi jauh lebih besar dari ini, mengingat transparansi dan kepatuhan pelaporan dana kampanye yang masih sangat rendah.
Hasil riset kami menemukan bahwa setidaknya ada empat faktor yang jadi penyebab melambungnya ongkos politik tersebut. Seluruhnya bermuara pada tidak efektifnya kebijakan pemilu yang berlaku saat ini, mulai dari sistem proporsional terbuka, keserentakan pemilu, lemahnya penegakan aturan hingga masih kentalnya praktik jual beli suara.
1. Sistem proporsional terbuka jadi ajang adu popularitas
Indonesia kini menganut sistem representasi proporsional daftar terbuka[3]. Dalam sistem representasi proporsional, partai mendapatkan jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara di daerah pemilihan/dapil). Sementara daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih langsung nama caleg.
Sepintas memang terlihat demokratis, tetapi sebenarnya kedua sistem ini telah membuat persaingan antarcalon menjadi lebih ketat dan kemudian mendorong biaya semakin melangit. Hal ini terjadi karena setiap caleg harus merayu langsung pemilih agar mencoblos nama mereka di Pileg. Persaingan popularitas menjadi tak terelakkan dan biaya memopulerkan diri di kalangan pemilih terus melambung seakan tidak ada batas atas.
Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk memperluas peluang calon agar lebih beragam, dalam praktiknya hal ini justru menyebabkan pemilu menjadi semacam kontes popularitas semata. Ketenaran dan kemampuan calon untuk membagi-bagikan sumber daya menjadi lebih berpengaruh kepada pemilih daripada ideologi atau diskusi agenda kebijakan.
Caleg yang sudah memiliki modal popularitas yang tinggi, misalnya selebritas atau anak kepada daerah, tentu mendapatkan keuntungan di sistem proporsional terbuka. Biaya untuk dikenal oleh pemilih menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang bukan dari dua latar belakang ini.
Komeng adalah salah satu contoh paling pas menjelaskan fenomena artis di Pileg 2024. Sebagai komedian yang sangat terkenal, ia mengaku tidak mengeluarkan modal yang besar bahkan tidak perlu kampanye[4] untuk memenangkan jutaan suara di Jawa Barat dan berhasil duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan.
Salah satu rekomendasi yang kami tawarkan adalah agar sistem proporsional terbuka dikaji ulang. Meskipun kembali ke sistem tertutup murni akan mengembalikan kontrol partai terhadap siapa caleg yang akan masuk parlemen, mekanisme ini akan menekan ongkos politik[5], memudahkan masyarakat menilai kinerja partai berdasarkan komposisi dan kualitas kader yang terpilih, dan partai akan lebih fokus memberikan pendidikan politik untuk kadernya yang dipersiapkan menjadi anggota legislatif.
2. Keserentakan pemilu
Keputusan pemerintah untuk mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg)—di tingkat nasional maupun daerah—secara serentak pada 2024 terbukti meningkatkan biaya pemilu.
Bagi caleg, jadwal yang bersamaan ini berarti mereka diharapkan tidak hanya berkampanye untuk pencalonan mereka sendiri tetapi juga untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang didukung oleh partai.
Di satu sisi, caleg yang partainya berada di koalisi pasangan capres dan cawapres yang didukung oleh penguasa mengaku mendapatkan dukungan logistik. “Tahun 2019, ketika partai saya mendukung Pak Jokowi, saya mendapatkan dana Rp2 miliar untuk membantu kampanye capres di dapil saya,” ujar salah satu narasumber.
Sementara caleg yang berada di koalisi kontra rejim berkuasa mengaku tidak mendapatkan tambahan bantuan dan harus berupaya lebih keras untuk memenangkan suara pemilih.
“Dengan dua pemilihan yang diadakan pada hari yang sama, pemilih tidak benar-benar fokus kepada caleg dan pileg. Hal ini terutama lebih sulit jika partai kami bukan bagian dari koalisi yang sedang berkuasa. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk menarik pemilih, dan dengan pemilih yang sebagian besar pragmatis, kerja keras kami jadi sia-sia,” kata narasumber lainnya.
Durasi kampanye dalam Pemilu 2024 hanya 75 hari, jauh lebih pendek daripada periode sebelumnya yaitu 200 hari. Namun biaya kampanye ternyata justru semakin tinggi. Faktor ketimpangan sumber daya antarcaleg akibat kompetisi para capres dan cawapres mendorong pengeluaran berkampanye terus meningkat.
Kami merekomendasikan agar pilpres dan pileg diselenggarakan secara terpisah agar pemilih dapat fokus memperhatikan materi yang ditawarkan para calon sesuai dengan persaingan yang dihadapi.
Opsi lain adalah menggabungkan pemilu berdasarkan cabang pemerintahan. Misalnya, di cabang ekskutif, pilpres dapat digabungkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara di cabang legislatif, Pileg untuk DPR-RI dapat diselenggarakan bersamaan dengan Pileg untuk DPRD.
3. Lemahnya penegakan aturan
Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten oleh penyelenggara pemilu juga menjadi faktor yang mendorong tingginya biaya politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara konsisten telah gagal menunjukkan komitmen yang serius untuk menindaklanjuti perbedaan antara laporan keuangan yang diajukan partai dan pengeluaran aktual di lapangan.
“Politik uang semakin liar karena Bawaslu menutup mata terhadapnya, begitu juga dengan polisi. Mereka semua menganggap politik uang sebagai hal yang normal. Tingkat kelalaian yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu membuat orang melakukan politik uang secara terang-terangan sekarang—tidak lagi bersembunyi atau berupaya menyamarkannya,” kata responden.
Narasumber dalam riset kami juga menyoroti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang cenderung tebang pilih[6] ketika menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran aturan kampanye yang kemudian mereka proses.
Inkonsistensi Bawaslu sangat jelas terlihat ketika cawapres Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu pada 19 November 2023 dan bagi-bagi susu di kawasan bebas kendaraan pada 3 Desember 2023. Bawaslu DKI menyatakan ada pelanggaran tapi kemudian dinihilkan oleh Bawaslu RI.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengkritik[7] Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye yang dinilainya kurang tegas sehingga membuat kegamangan penegakan hukum. Ia mencontohkan ketidakjelasan aturan mengenai politik uang, seperti bazar dan doorprize, yang akhirnya membuat Bawaslu menerapkan aturan teknis sendiri untuk menetapkan batasan nilai maksimum.
Dari sini kami merekomendasikan agar Bawaslu dibekali dengan wewenang yang lebih besar dan lebih jelas untuk memantau kepatuhan serta menegakkan sanksi terhadap pelanggar integritas pemilu di semua tahapan. Selain itu, saluran partisipasi publik dalam memantau kepatuhan aturan pemilu, misalnya melalui saluran pengaduan khusus dan/atau mekanisme pengaduan, harus diperkuat dan diperluas.
4. Budaya jual beli suara
Budaya pembelian suara yang semakin marak dan semakin diterima membuat biaya politik terus meningkat. Membeli suara telah menjadi hal yang lumrah[8] dalam politik Indonesia. Kampanye kini lebih banyak tentang membagikan hadiah dan insentif uang sebagai imbalan atas suara; sebuah kenyataan yang tampaknya telah diterima oleh politikus dan sebagian besar masyarakat.
Beberapa responden secara terbuka mengakui telah membagikan uang dalam amplop untuk membeli suara melalui tim kampanye mereka, sementara yang lain mengklaim bahwa hanya lawan politik mereka yang melakukan itu, dengan angka berkisar antara Rp100–500 ribu.
Meskipun tindakan ini melanggar Undang-undang (UU) Pemilu, namun nyatanya jual beli suara sudah menjadi praktik yang lazim. Terbatasnya pendidikan pemilih dan kesulitan ekonomi dipandang sebagai dua faktor utama yang berkontribusi terhadap normalisasi pembelian suara.
Sebagai rekomendasi menekan praktik jual beli suara, kami mendesak agar KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja sama lebih lanjut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aktivitas keuangan mencurigakan terkait pendanaan politik selama siklus pemilu.
Pada 10 Januari 2024, PPATK mengumumkan ada 100 caleg yang memiliki transaksi mencurigakan[9] dengan total nominal Rp51 triliun. Sampel caleg yang terendus oleh PPATK ini juga ternyata menerima dana dari luar negeri hingga Rp7 triliun.
Sebagai perbandingan, dana penyelenggaraan Pemilu 2024[10] adalah Rp71,3 triliun atau naik 57% dari Pemilu 2019. Transaksi mencurigakan yang semasif ini sudah sepatutnya ditelusuri oleh KPU dan Bawaslu untuk memastikan jejak pembiayaan jual-beli suara agar kemudian dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.
References
- ^ Riset terbaru (www.costofpolitics.net)
- ^ empat tahapan pemilu (theconversation.com)
- ^ sistem representasi proporsional daftar terbuka (www.mkri.id)
- ^ tidak perlu kampanye (www.liputan6.com)
- ^ menekan ongkos politik (news.detik.com)
- ^ tebang pilih (www.kompas.id)
- ^ Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengkritik (www.kompas.id)
- ^ hal yang lumrah (rumahpemilu.org)
- ^ 100 caleg yang memiliki transaksi mencurigakan (news.detik.com)
- ^ dana penyelenggaraan Pemilu 2024 (jdih.bpk.go.id)
Authors: Ella Syafputri Prihatini, Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta