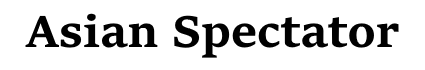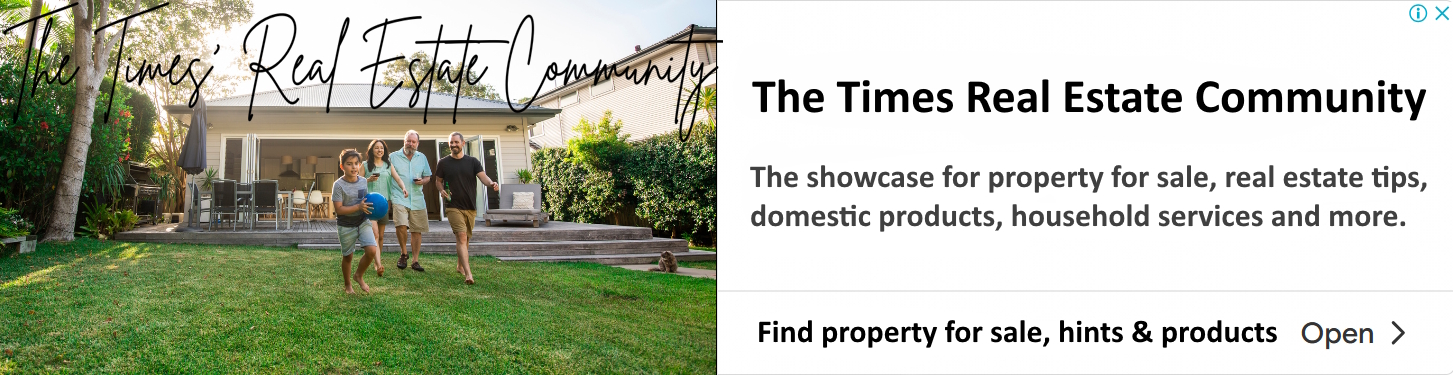“Sudah menikah?” “Sudah berapa anaknya?”: bagaimana pertanyaan basa-basi ini bisa menjadi stigma
- Written by Nelly Martin-Anatias, Lecturer of Academic English at Massey University College, Massey University

Tina, seorang perempuan berusia awal 40-an, berasal dari salah satu negara di Asia Tenggara, adalah seorang pribadi yang telah sukses dengan dua gelar pendidikan tinggi.
Tina sudah tinggal bertahun-tahun di Selandia baru. Berada jauh dari negara dan keluarganya selama bertahun-tahun, Tina menganggap komunitas lokal Asia Tenggara di Selandia Baru seperti keluarga barunya. Namun, berinteraksi dengan mereka berarti dia harus menghadapi beberapa pertanyaan yang mengganggu seperti “Apakah kamu sudah menikah?” atau “Apakah Anda punya anak?” saat menghadiri pesta pernikahan saudara atau kolega.
“Kami paham bahwa mereka orang baik dan pertanyaan itu tidak bermaksud untuk menyakiti kami, namun, saat pertanyaan itu berulang, bahkan oleh orang yang kami baru kenal sekalipun, kami menjadi tidak nyaman.”
“Pertanyaan itu, seperti menggarisbawahi hal yang kami, saya tidak punya, dan tidak melihat apa yang sudah kami capai dalam hidup. Saya paham bahwa stigma itu selalu ada…,"ujar Tina yang memang mengalami kesulitan untuk memiliki anak bersama suaminya.
Bagi Tina, apa yang selama ini dianggap sebagai sapaan sosial yang "normal” di kalangan masyarakat Asia dirasakan sebagai stigma terhadap perempuan yang belum menikah dan tidak memiliki anak.
Tina tidak sendirian merasakan hal ini.
Proyek penelitian kami yang saat ini masih berlangsung berusaha membongkar bagaimana pertanyaan tentang anak-anak dapat membawa stigma. Kami menemukan pertanyaan-pertanyaan ini berdampak pada harga diri dan hubungan perempuan dengan keluarga dan komunitas mereka.
Ada apa dengan pertanyaan “basa-basi” ini?
Fokus utama penelitian kami adalah perempuan dan pasangan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kami mewawancarai 23 perempuan – termasuk perempuan yang kami panggil Tina – yang bermigrasi dari negara kelahiran mereka ke Aotearoa Selandia Baru. Responden ini (pernah) mengalami masalah kesuburan dan tidak bisa punya anak.
Temuan penelitian awal kami menunjukkan bahwa pertanyaan seperti “Apakah Anda sudah menikah?” dan “Apakah Anda punya anak?” memiliki interpretasi yang berbeda baik dari sisi penanya maupun responden.
Dari sudut pandang penanya, pertanyaan semacam itu dianggap sebagai sapaan yang umum. Mereka sebanding dengan “Apa kabar?” di dunia Barat.
Pertanyaan tersebut muncul dari asumsi bahwa setiap perempuan dewasa di sebagian besar negara Asia adalah heteroseksual, menikah dan, mungkin, seorang ibu.
Dengan asumsi bahwa setiap orang pasti menikah dengan lawan jenis dan akhirnya menjadi ibu, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bagian dari pemahaman sosial mereka. Narasumber kami memahami bahwa pertanyaan tidak selalu bermaksud buruk dan semua itu harus dipahami sebagai “konvensi sosial” atau bagian dari “obrolan atau sapaan sehari-hari”.