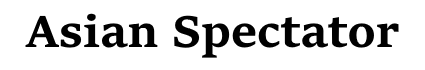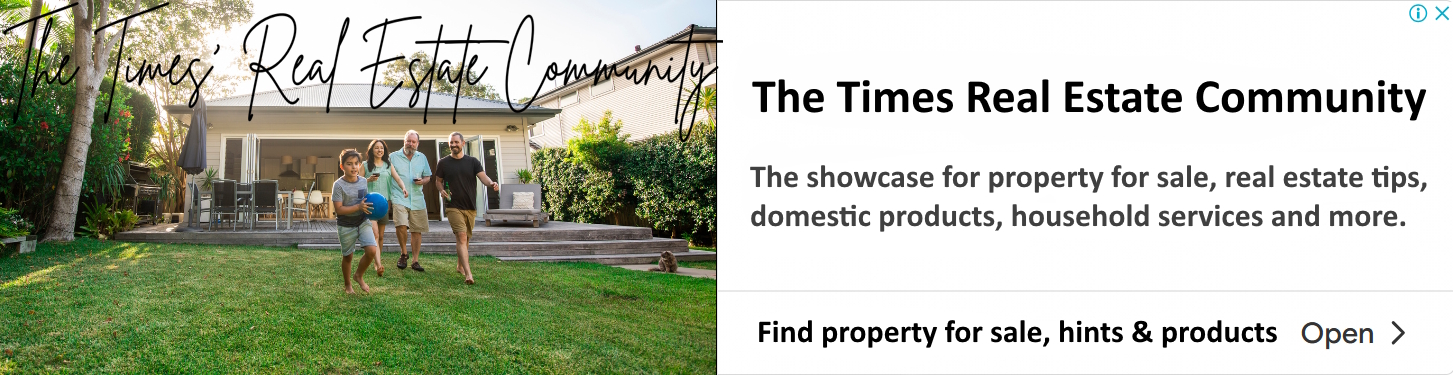Demokrasi vs intervensi: Mengapa Barat dan ‘Global South’ punya perspektif berbeda tentang kedaulatan
- Written by Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Situasi Geopolitik di Kawasan Timur Tengah masih memanas. Israel masih terus-menerus membombardir kota-kota di Suriah. Israel tampaknya tengah memanfaatkan situasi Suriah yang saat ini sedang bergejolak pasca-kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang telah berkuasa selama 24 tahun.
Kejatuhan rezim Assad di satu sisi memang memberikan harapan baru bagi para pengungsi,[1] yang selama ini menjadi korban kekejaman pemerintahannya[2]. Namun di sisi lain, kekosongan kekuasaan, ketidakstabilan politik domestik, ditambah dengan keaadan sosial ekonomi rakyat yang buruk[3], membuka peluang bagi aktor-aktor eksternal[4] untuk memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi.
Dalam mengulas isu Suriah dan konflik di Timur Tengah, tulisan dan narasi di media arus utama lebih banyak didominasi oleh perspektif mainstream ala Barat[5]. Misalnya seperti The New York Times yang fokus pada penggambaran konflik Suriah sebagai perjuangan antara pemerintahan otoriter Assad melawan kelompok oposisi “pro-demokrasi”. Media ini cenderung menyoroti tindakan represif Assad sebagai akar konflik[6] tanpa menggali lebih dalam peran negara-negara Barat sendiri, termasuk Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, dalam melakukan intervensi asing.
Melalui tulisan ini, saya ingin menguraikan mengapa terjadi perbedaan interpretasi konsep kedaulatan antara Barat dan non-Barat serta apa yang bisa dipelajari oleh negara-negara Selatan (‘Global South’) dari konflik di Timur Tengah.
Barat vs ‘Global South’
Samuel P. Huntington, profesor politik di Universitas Harvard, mengkategorikan negara-negara Barat dalam karyanya “The Clash of Civilization[7]” sebagai AS, Kanada, Eropa Barat dan Tengah, Australia, dan Oseania. Huntington menekankan kesamaan budaya dan agama, khususnya Kristen Barat, sebagai ciri khas negara-negara Barat. Ia mengategorikan Israel[8] sebagai bagian dari peradaban Barat karena akar budaya Yudeo-Kristen, pemerintahan yang demokratis, dan afiliasi yang kuat dengan Barat.
Mantan kanselir Jerman, Willy Brandt, memperkenalkan konsep “Utara-Selatan” sebagai pembagian geografis yang membedakan Utara yang makmur dengan Selatan yang miskin[9]. Namun, simplifikasi geografis ini banyak dikritik karena mengabaikan realitas ketidaksetaraan yang kompleks, di mana ada daerah kaya di Selatan (misalnya, Australia) dan daerah miskin masih bisa ditemukan di Utara (misalnya, beberapa bagian Eropa Timur).
Salah satu yang mengkritik adalah Felix Lamech Mogambi Ming'ate, profesor Universitas Kenyatta di Kenya[10]. Ia menekankan ‘Global South’[11] sebagai identitas sosiopolitik yang mencakup negara-negara di Afrika, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia, yang disatukan oleh perjuangan bersama melawan kemiskinan, kerusakan lingkungan karena imbas dari Barat dan tantangan sosial yang berakar pada warisan kolonial. Contohnya adalah Indonesia yang masih menjadi tempat pembuangan sampah dari Barat[12].
Pandangan Barat: Intervensi berkedok demokrasi
Secara tradisional, kedaulatan dalam teori hubungan internasional Barat berakar pada prinsip-prinsip sistem negara modern dalam perjanjian Westphalia tahun 1648[13]. Westphalia[14] menekankan pada integritas teritorial, tidak campur tangan urusan dalam negeri orang lain (non-intervensi), dan kesetaraan semua negara di bawah hukum internasional.
Dalam praktiknya, negara-negara Barat sering kali memaknai konsep kedaulatan secara fleksibel, untuk membenarkan intervensi atas nama kepentingan kemanusiaan, mempromosikan demokrasi, atau memerangi terorisme[15]. Penerapan yang selektif ini dianggap sebagai standar ganda dalam menghormati kedaulatan, melemahkan prinsip non-intervensi, terutama di negara-negara ‘Global South’.
Sebagai contoh[16], standar ganda Barat terhadap penjajahan Israel di Palestina terlihat dalam dukungan politik dan militer yang terus diberikan kepada Israel, meskipun ada laporan pelanggaran HAM dan hukum internasional. Sementara itu, Barat sering mengutuk pelanggaran serupa di negara lain.
Contoh lainnya adalah intervensi NATO di Libya pada 2011[17] dengan dalih doktrin “Responsibility to Protect” (R2P) yang memicu kritik keras dari ‘Global South7[18]. Bagi negara 'Global South’[19], misalnya Iran[20], yang tergabung dalam BRICS, intervensi tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan campur tangan penggantian rezim yang dibungkus alasan kemanusiaan.
Ada pula invasi AS ke Irak pada 2003[21], yang dilakukan dengan klaim senjata pemusnah massal (WMD). Klaim tersebut pada akhirnya tidak terbukti namun Irak terlanjur porak-poranda karena invasi.
Tidak hanya itu, pada tahun 2019, AS dan beberapa negara Barat, termasuk sebagian besar negara di Eropa, mengakui Juan Guaidó, pemimpin oposisi Venezuela, sebagai presiden interim menggantikan Nicolás Maduro[22]. Ini tentu saja bertentangan dengan prinsip nonintervensi yang menekankan hak negara atas penentuan nasib sendiri.
Prinsip non-Barat: Kedaulatan melawan dominasi eksternal
Sebaliknya, bagi banyak negara non-Barat, kedaulatan dipahami sebagai alat untuk melawan dominasi eksternal, melindungi otonomi dari pengaruh negara-negara yang pernah menjajah mereka, serta menjaga pembangunan dan identitas budaya.
Negara ‘Global South’, yang secara historis mengalami penjajahan, ketergantungan ekonomi, dan marginalisasi dalam sistem internasional[23] menggunakan kedaulatan untuk melindungi kebijakan domestik dari tekanan negara maju dan lembaga keuangan internasional yang sering memaksakan agenda yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.
Contohnya saat India menolak persyaratan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)[24] yang dianggap merugikan petani lokal. India mempertahankan kebijakan subsidi pertanian untuk melindungi petaninya dari ketergantungan pasar global dan tekanan negara maju yang mendorong liberalisasi ekonomi.
Contoh lain adalah Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales[25], yang menasionalisasi industri gas dan minyak sebagai langkah untuk mengembalikan kontrol sumber daya alam kepada negara, melindungi kedaulatan ekonominya dari dominasi perusahaan multinasional.
Pelajaran bagi ‘Global South’
1. Memperkuat persatuan dan tata kelola pemerintahan
Ketidakstabilan politik, perpecahan sosial, krisis ekonomi di dalam negeri akan membuat sebuah negara sangat rentan terhadap manipulasi, propaganda dan intervensi dari luar. Buktinya, konflik Suriah berawal dari perbedaan opini publik mengenai masalah tata kelola pemerintahan, yang berkembang menjadi perang saudara karena tidak ada penyelesaian.
Negara-negara ‘Global South’ dapat mempelajari pentingnya menjaga persatuan negara secara konstan, mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif, memberantas korupsi, dan mendengarkan aspirasi dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan, serta mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial untuk mencegah konflik internal meningkat menjadi krisis.
2. Membangun kemandirian ekonomi
Di Suriah, misalnya, sanksi dan embargo eksternal sangat melumpuhkan perekonomian, sehingga negara ini bergantung pada sekutu untuk bertahan hidup. Ini merupakan pelajaran penting untuk memprioritaskan kemandirian ekonomi, termasuk memastikan produksi pangan dalam negeri cukup sehingga tidak terlalu bergantung pada impor.
Negara ‘Global South’ juga perlu didorong untuk mengembangkan energi terbarukan lokal melalui eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan kebutuhan pokok sehingga lebih tahan terhadap embargo maupun gangguan rantai pasok global.
3. Menegakkan prinsip non-blok
Suriah menjadi medan pertempuran bagi kekuatan global dan regional yang memiliki pertentangan kepentingan. Ketergantungan Suriah pada blok tertentu seperti Rusia dan Iran, membuat kedaulatannya sangat bergantung pada kekuatan eksternal yang sebenarnya memiliki kepentingan mereka sendiri, sekaligus turut menjadi target bagi negara-negara yang berseberangan blok.
Negara-negara ‘Global South’ lainnya harus berusaha untuk tidak memihak pada blok kekuatan besar, seperti yang dilakukan Indonesia, India, Kuba dan Afrika Selatan, dengan mendiversifikasi hubungan internasional untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan.
4. Menjaga solidaritas regional dan multilateral
Solidaritas regional seperti African Union (AU) dan ASEAN menekankan prinsip non-interferensi, berlawanan dengan praktik negara Barat yang sering membenarkan intervensi dengan alasan norma-norma internasional.
Negara-negara ‘Global South’ dapat memperkuat organisasi regional atau organisasi multilateral untuk menciptakan norma-norma, serta mekanisme kolektif dalam penyelesaian konflik tanpa gangguan eksternal. Misalnya, melalui aliansi ekonomi BRICS yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
5. Berinvestasi pada keamanan siber
Konflik di Suriah tidak murni militer namun juga melibatkan beragam operasi siber hingga propaganda media. Negara-negara ‘Global South’ dapat membangun infrastruktur siber dan pelatihan tenaga ahli untuk melindungi diri dari ancaman seperti serangan ransomware atau hacking terhadap jaringan listrik nasional, pencurian data oleh aktor negara atau kelompok non-negara untuk keuntungan mereka sendiri.
Ini penting untuk mencegah upaya pihak tertentu memaanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau memanipulasi opini publik, hingga mengorganisir serangan atau menyebarkan ideologi radikal.
Kedaulatan dan persatuan harga mati
Sebagai negara yang pernah mengalami dominasi kekuasaan (penjajahan), negara-negara ‘Global South’ harus mampu terhindar dari jebakan poskolonialisme (penjajahan baru), seperti menjadi negara perantara perang (proxy) dari rivalitas kekuatan global, ketergantungan ekonomi, hingga intervensi pihak asing, atas nama kemanusiaan, promosi demokrasi, maupun darurat militer.
Sebaliknya, Global South harus mampu menjadi percontohan bagi prinsip non-intervensi, menghormati kedaulatan negara lain, dan menjaga perdamaian dunia.
References
- ^ memberikan harapan baru bagi para pengungsi, (www.npr.org)
- ^ korban kekejaman pemerintahannya (timep.org)
- ^ kekosongan kekuasaan, ketidakstabilan politik domestik, ditambah dengan keaadan sosial ekonomi rakyat yang buruk (www.iemed.org)
- ^ membuka peluang bagi aktor-aktor eksternal (ijsoc.goacademica.com)
- ^ didominasi oleh perspektif mainstream ala Barat (www.nytimes.com)
- ^ menyoroti tindakan represif Assad sebagai akar konflik (www.nytimes.com)
- ^ The Clash of Civilization (www.guillaumenicaise.com)
- ^ mengategorikan Israel (www.ispionline.it)
- ^ Willy Brandt, memperkenalkan konsep “Utara-Selatan” sebagai pembagian geografis yang membedakan Utara yang makmur dengan Selatan yang miskin (bigthink.com)
- ^ Felix Lamech Mogambi Ming'ate, profesor Universitas Kenyatta di Kenya (gssc.uni-koeln.de)
- ^ menekankan ‘Global South’ (kups.ub.uni-koeln.de)
- ^ tempat pembuangan sampah dari Barat (www.dw.com)
- ^ perjanjian Westphalia tahun 1648 (www.sciencedirect.com)
- ^ Westphalia (www.jstor.org)
- ^ membenarkan intervensi atas nama kepentingan kemanusiaan, mempromosikan demokrasi, atau memerangi terorisme (www.paradigmshift.com.pk)
- ^ Sebagai contoh (mediaindonesia.com)
- ^ intervensi NATO di Libya pada 2011 (natoassociation.ca)
- ^ kritik keras dari ‘Global South7 (www.globalr2p.org)
- ^ Bagi negara 'Global South’ (academic.oup.com)
- ^ misalnya Iran (foreignpolicy.com)
- ^ invasi AS ke Irak pada 2003 (www.tandfonline.com)
- ^ mengakui Juan Guaidó, pemimpin oposisi Venezuela, sebagai presiden interim menggantikan Nicolás Maduro (www.theguardian.com)
- ^ penjajahan, ketergantungan ekonomi, dan marginalisasi dalam sistem internasional (academic.oup.com)
- ^ India menolak persyaratan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (www.wto.org)
- ^ Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales (www.opendemocracy.net)
Authors: Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo