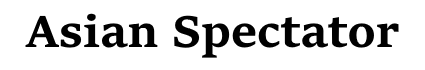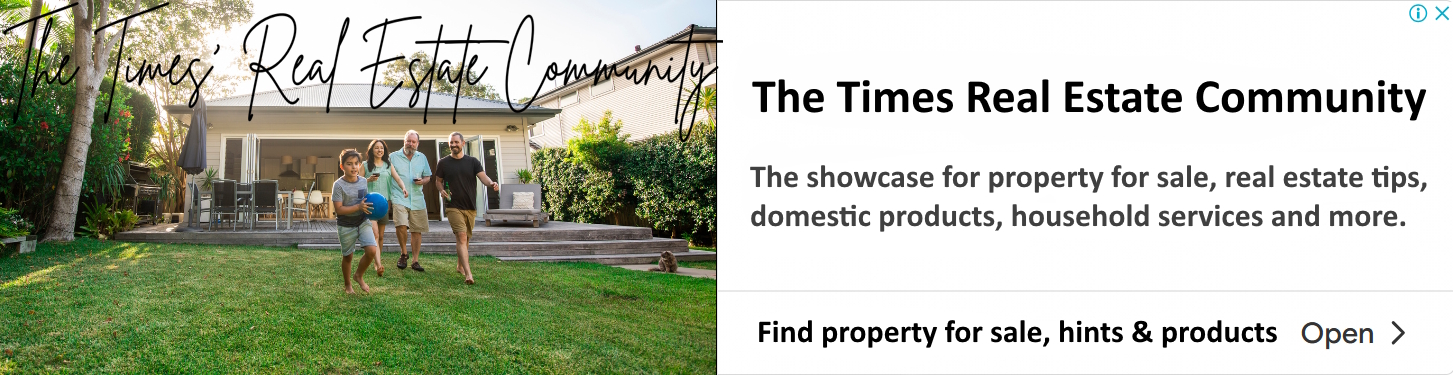Kesenjangan digital menghambat penyandang disabilitas untuk terlibat aktivisme daring: apa yang harus dilakukan pemerintah?
- Written by Widowati Maisarah, Mahasiswa Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada

Dunia siber adalah arena penting bagi komunitas kelompok disabilitas untuk melakukan aktivisme digital[1].
Aktivisme digital[2] sangat bermanfaat bagi kelompok disabilitas karena sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah. Ini memberi ruang untuk munculnya gerakan di satu sudut bumi yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi kelompok lain yang lokasinya jauh secara geografis.
Bagi kelompok-kelompok minoritas secara khusus, aktivisme digital memudahkan penyuaraan aspirasi dan kampanye gerakan-gerakan sosial tertentu melalui media siber.
Pada bulan April 2022, misalnya, sejumlah penyandang disabilitas sempat melakukan protes[3] atas diskriminasi yang mereka alami ketika mendaftar sebagai pengemudi ojek daring. Namun, aksi protes tersebut masih menggunakan cara konvensional, yaitu berdemonstrasi langsung di depan kantor perusahaan ojek daring.
Padahal, mereka seharusnya bisa membuat petisi daring untuk menggalang dukungan yang lebih kuat dari para warganet.
Aktivisme digital semacam ini penting dilakukan agar kelompok disabilitas, sebagai minoritas, dapat memperjuangkan hak-hak dan aspirasinya[4] dengan efektif, cepat, dan tepat sasaran.
Namun demikian, masih banyak tantangan dan hambatan yang harus mereka hadapi supaya bisa terlibat dalam aktivisme digital secara bermakna. Penyebab utamanya adalah masih lebarnya kesenjangan digital (digital divide) bagi penyandang disabilitas.
Kendala kesenjangan digital
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016[5] tentang Penyandang Disabilitas sebenarnya telah mengakomodir hak-hak atas akses informasi bagi kelompok tersebut. Sayangnya, hak-hak ini belum bisa sepenuhnya terpenuhi karena masih lebarnya kesenjangan digital yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018[6] oleh Kementerian Sosial menunjukkan bahwa akses informasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia dalam penggunaan telepon seluler dan laptop masih cukup rendah, yakni 34,89%, sedangkan kelompok non disabilitas 81,61 %.
Menurut pembaruan data Susenas[7] tahun 2020, kepemilikan telepon seluler penyandang disabilitas hanya naik sedikit, yaitu jadi sebesar 36,74%. Akses penyandang disabilitas terhadap internet pun hanya mencapai 8,50%, sementara non disabilitas 45,46%.
Menurut beberapa penelitian[8], faktor utama yang menyebabkan kesenjangan digital di antara penyandang disabilitas adalah lemahnya motivasi dan kurangnya ketertarikan mereka untuk mengakses teknologi digital.
Keterbatasan fisik, faktor ekonomi dan beban biaya, kapasitas penguasaan teknologi, ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta rendahnya dukungan sosial menjadi alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat motivasi mereka.
Di Indonesia, sebagian besar penyandang disabilitas kurang sejahtera dibanding non-disabilitas.
Data Susenas 2020, misalnya, menyatakan sebanyak 71,4% penduduk penyandang disabilitas merupakan pekerja informal. Tingkat kemiskinan kelompok tersebut mencapai 11,42%[9], lebih tinggi dari tingkat kemiskinan kelompok non-disabilitas yang sebesar 9,63%.
Sekalipun ada sebagian penyandang disabilitas yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, mereka tetap cenderung merasakan intimidasi teknologi[10] dan masih tertinggal dari kelompok non-disabilitas dalam penggunaan media digital. Ini karena adanya hambatan aksesibilitas teknis. Misalnya, tunanetra kesulitan mengakses media digital yang tidak dilengkapi perangkat pengubah teks menjadi suara.
Penyandang disabilitas dengan pendapatan level menengah pun tetap harus mengeluarkan biaya tambahan[11] untuk memperoleh teknologi adaptif yang didesain khusus untuk pengguna disabilitas. Ini karena ketersediaan perangkat yang dapat mendukung dan membantu pengguna disabilitas masih sangat minim[12].
Teknologi adaptif sebagai alat bantu tidak hanya sulit dipelajari dan mahal, tetapi juga lambat dalam pengembangannya.
Sebagai contoh, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat (AS) mencoba mengembangkan sistem huruf[13] yang bisa menerjemahkan alfabet biasa ke braille (sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh penyandang tunanetra) secara real-time.
Teknologi adaptif ini memudahkan penyandang tunanetra untuk membaca teks huruf biasa, walaupun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat memindai teks digital. Tapi, selain mahal, teknologi adaptif semacam ini juga hanya terbatas bagi penyandang tunanetra yang sudah punya tingkat literasi tertentu.
Para produsen perangkat teknologi pun menghadapi tantangan[14] karena kebutuhan penyandang disabilitas tentu saja berbeda-beda. Kebutuhan teknologi bagi penyandang tunanetra, misalnya, tentu berbeda dengan penyandang tunarungu. Sementara itu, untuk menciptakan perangkat teknologi yang sangat universal – yang bisa diakses semua kelompok penyandang disabilitas – pasti membutuhkan biaya tinggi dan hal tersebut akan mempengaruhi harga penjualannya di pasar.
Meski demikian, teknologi adaptif ini sangat diperlukan oleh para penyandang disabilitas untuk dapat mengakses media digital dan internet.
Menjembatani kesenjangan digital
Penting bagi penyandang disabilitas untuk bisa menyampaikan gagasan, aspirasi, dan hak-hak mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesehatan mental, dan modal sosial. Kesenjangan terkait aktivisme digital dapat memperparah kerugian sosial ekonomi[15] yang sudah dihadapi penyandang disabilitas.
Setidaknya ada dua langkah utama yang bisa pemerintah lakukan untuk menjembatani kesenjangan ini guna mendukung penyandang disabilitas mengejar ketertinggalan dalam mengakses teknologi dan terlibat aktivisme digital.
Pertama, merumuskan kebijakan yang dapat mendukung transformasi digital bagi kelompok disabilitas.
Wacana Transformasi Digital[16] yang digaungkan oleh pemerintah harus bersifat inklusif. Kebijakan pemerintah harus dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, maupun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kedua, selain menyediakan akses digital yang merata melalui penyediaan infrastruktur dan platform pelayanan publik digital, pemerintah harus menyediakan akses dengan biaya yang terjangkau bagi kelompok penyandang disabilitas.
Misalnya, pemerintah dapat menerapkan skema insentif dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan dan produk teknologi untuk meningkatkan ketersediaan teknologi adaptif.
Dengan menjembatani kesenjangan digital tersebut, pemerintah sudah satu langkah lebih maju dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan mendukung peningkatan aktivisme digital. Pada akhirnya, ini akan mendukung terwujudnya demokrasi dan keadilan di Indonesia.
Artikel ini merupakan salah satu pemenang Kompetisi Menulis dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-5 The Conversation Indonesia.
References
- ^ aktivisme digital (core.ac.uk)
- ^ Aktivisme digital (doi.org)
- ^ melakukan protes (megapolitan.kompas.com)
- ^ hak-hak dan aspirasinya (doi.org)
- ^ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (peraturan.bpk.go.id)
- ^ Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 (kemensos.go.id)
- ^ pembaruan data Susenas (kemensos.go.id)
- ^ beberapa penelitian (doi.org)
- ^ 11,42% (perpustakaan.bappenas.go.id)
- ^ merasakan intimidasi teknologi (doi.org)
- ^ mengeluarkan biaya tambahan (doi.org)
- ^ sangat minim (doi.org)
- ^ mengembangkan sistem huruf (tekno.kompas.com)
- ^ menghadapi tantangan (doi.org)
- ^ memperparah kerugian sosial ekonomi (www.researchgate.net)
- ^ Transformasi Digital (www.djkn.kemenkeu.go.id)
Authors: Widowati Maisarah, Mahasiswa Doktoral Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada