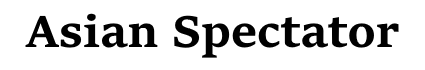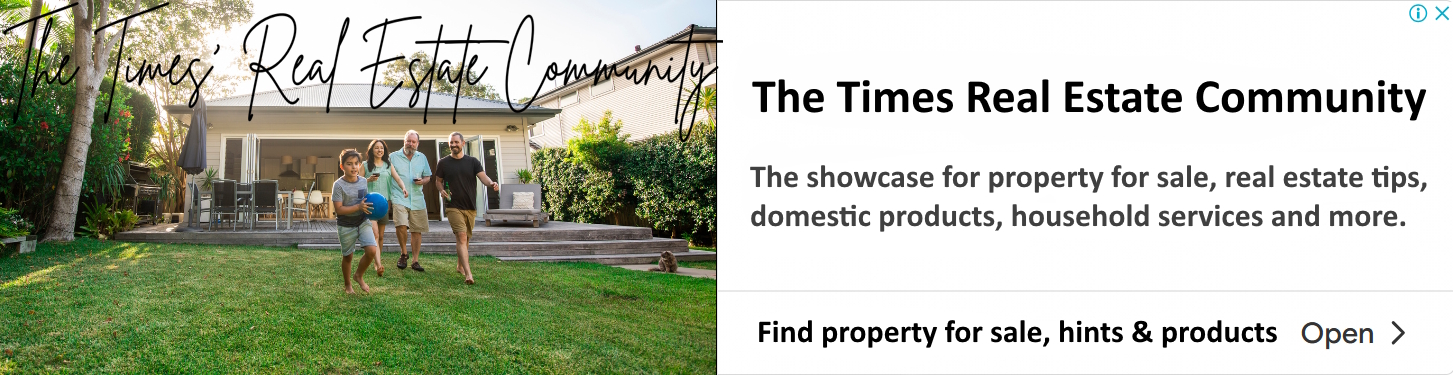Politisasi agama: Bagaimana elite menyalahgunakan simbol spiritual untuk mengendalikan opini publik
- Written by Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

● Elite politik kerap memanfaatkan momen keagamaan untuk membangun citra moral.
● Publik harus kritis untuk menilai apakah kepedulian yang ditunjukkan oleh elite politik hanya bersifat seremonial.
● Bersikap kritis terhadap politisasi agama bukan berarti menolak agama dalam kehidupan keseharian kita.
Bulan Ramadan lalu, serupa dengan periode bulan cuti sebelum-sebelumnya, kita banyak menyaksikan kegiatan pemberian bantuan sosial[1] kepada masyarakat dari aktor negara, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pejabat-pejabat dan figur politik.
Pemberian bantuan sosial tentunya bukan hal salah, apalagi di momen Ramadan yang lekat dengan aktivitas solidaritas sosial dan penguatan identitas keislaman.
Namun, publik sebaiknya tetap berpikir bijak dan kritis. Sebab, tanpa kita sadar, momen keagamaan kerap kali dipolitisasi oleh elite politik, terutama sebagai kesempatan untuk membangun citra moral.
Melalui berbagai aksi kepedulian, seperti distribusi bantuan sosial[2], buka puasa[3] bersama kaum dhuafa, hingga retorika kebijakan[4] yang menekankan kesejahteraan rakyat, elite politik memainkan simbol-simbol religius dan memanfaatkan atmosfer emosional pemeluk agama.
Agama dalam politik dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi, ia bisa menjadi pendorong moralitas dan kebijakan yang lebih adil, tetapi di sisi lain, ia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan populisme dan manipulasi. Masyarakat harus lebih berhati-hati.
Pengaruh psikologis simbol agama
Simbol agama dalam konteks kini bisa dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk momen bulan suci Ramadan dan peringatan keagamaan lainnya.
Sejumlah penelitian[6] menunjukkan bahwa penggunaan simbol agama sering kali menjadi strategi efektif bagi elite politik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat legitimasi kekuasaan dan memperkuat dukungan elektoral.
Ini karena persepsi publik terhadap komitmen nasional kelompok agama berpengaruh besar terhadap penerimaan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik.
Selain itu, sebuah riset psikologi politik[7] menyebutkan bahwa paparan simbol agama dapat memengaruhi keadaan psikologis individu dan meningkatkan efek positif terhadap individu tersebut. Dengan demikian, penggunaan simbol agama dalam politik dapat meningkatkan keterikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat.
Salah satu contoh konkretnya adalah bagaimana politikus di Indonesia memanfaatkan simbol dan aktivitas keagamaan selama bulan Ramadan untuk membangun citra positif di mata publik. Misalnya, setiap tahun menjelang pemilihan umum (pemilu), banyak tokoh politik yang aktif[8] menggelar acara buka puasa bersama di pesantren-pesantren atau masjid besar. Ini tidak hanya menunjukkan kedekatan mereka dengan umat Islam tetapi juga memperkuat kesan kepedulian terhadap rakyat kecil.
Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdoğan[9], sering menggunakan retorika keagamaan dalam pidato-pidatonya dan hadir dalam berbagai acara keagamaan untuk mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang religius dan dekat dengan nilai Islam.
Praktik seperti ini juga tak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Di Amerika Serikat (AS), politikus dari Partai Republik sering kali menggunakan frasa seperti “God bless America”[10] atau menghadiri acara doa bersama untuk memperkuat legitimasi moral mereka di hadapan pemilih beragama.
Menutupi ‘dosa’ pemerintah
Penelitian lainnya[11] menunjukkan bahwa simbol agama dalam politik juga dapat disalahgunakan oleh oknum negara untuk menutupi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Riset lainnya[13] juga menyebutkan bahwa populisme sayap kanan sering kali menggunakan agama sebagai alat politik untuk mengendalikan opini publik dan mempertahankan kekuasaan.
Sebagai contoh, ada seorang pemimpin yang sering hadir dalam acara keagamaan dan undangan dari komunitas-komunitas berbasis agama[14]. Namun, dalam praktik kenegaraan, ia mengesahkan aturan-aturan yang tidak berpihak pada perekonomian rakyat menengah ke bawah dan menjalankan budaya nepotisme alias bagi-bagi ‘kue’ jabatan untuk elite terdekatnya. Akan tetapi, praktik tersebut seakan tak tampak karena pemimpin itu tampil sebagai figur religius.
Hal yang mengerikan dari fenomena politik identitas berbasis agama sering kali menutup ruang diskusi yang rasional dan konstruktif, karena lawan politik yang berseberangan dapat dengan mudah dicap sebagai “antiagama” atau “tidak menghormati nilai religius.”
Ini seharusnya menjadi alarm bagi publik agar tidak mudah terbuai dengan citra religius yang dibangun. Kritisisme terhadap politisasi agama menjadi sangat penting.
Publik jangan terbuai
Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis dalam merespons berbagai tindakan para elite politik. Publik perlu terus mempertanyakan apakah kepedulian yang ditunjukkan oleh elite politik hanya bersifat seremonial atau benar-benar berdampak dalam kebijakan nyata.
Sikap kritis ini akan sangat penting, agar kita tidak terjebak dalam pencitraan seremonial elite politik yang sering kali menutupi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dengan terus mempertanyakan kepedulian yang ditampilkan, masyarakat dapat mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar citra.
Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran kritis adalah dengan mengandalkan media independen dan platform akademis yang menyediakan analisis objektif terkait praktik politik berbasis agama. Sebuah penelitian tentang media dan agama[15] menyoroti bagaimana media berperan penting dalam membentuk opini publik dengan menyajikan simbol agama sebagai bagian dari wacana politik.
Oleh sebab itu, kita perlu lebih selektif dalam mengonsumsi informasi dan menghindari terpaan berita yang hanya memperkuat narasi populis tanpa analisis kritis.
Selain itu, kita perlu menghadirkan lebih banyak diskusi publik mengenai hubungan antara agama dan politik. Studi[17] tentang agama dan ruang publik menekankan pentingnya ruang musyawarah bagi masyarakat untuk dapat mendiskusikan peran agama dalam politik secara rasional dan berbasis data. Dengan cara ini, masyarakat dapat menghindari polarisasi yang sering kali muncul akibat politisasi agama.
Publik harus menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dari para pemimpin. Dengan langkah ini, keterbukaan dan kepentingan untuk rakyat terus terarah. Tidak cukup hanya menilai seorang pemimpin dari simbol-simbol keagamaan yang ia tampilkan, tetapi juga melihat kebijakan dan tindakan nyata yang dilakukan.
Jika seorang pemimpin sering berbicara tentang pentingnya nilai-nilai keagamaan, tetapi gagal menghadirkan kebijakan yang melindungi kaum miskin, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperjuangkan keadilan, maka dukungan terhadap pemimpin tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
Bersikap kritis terhadap politisasi agama bukan berarti menolak agama dalam kehidupan publik, tetapi justru berusaha menjaga kemurnian nilai-nilai agama agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Sebab, ketika agama hanya dijadikan alat politik, maka ia kehilangan esensinya sebagai sumber moralitas dan keadilan sosial yang sejati.
References
- ^ kegiatan pemberian bantuan sosial (regional.kontan.co.id)
- ^ bantuan sosial (www.liputan6.com)
- ^ buka puasa (kaltimtoday.co)
- ^ retorika kebijakan (www.kompas.com)
- ^ onyengradar/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ penelitian (www.cambridge.org)
- ^ sebuah riset psikologi politik (www.sciencedirect.com)
- ^ tokoh politik yang aktif (www.tempo.co)
- ^ Recep Tayyip Erdoğan (sg.news.yahoo.com)
- ^ “God bless America” (slate.com)
- ^ Penelitian lainnya (www.journals.uchicago.edu)
- ^ Drolink/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Riset lainnya (brill.com)
- ^ berbasis agama (www.tempo.co)
- ^ Sebuah penelitian tentang media dan agama (dx.doi.org)
- ^ Surya Htg/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Studi (link.springer.com)
Authors: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia