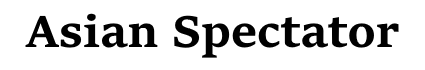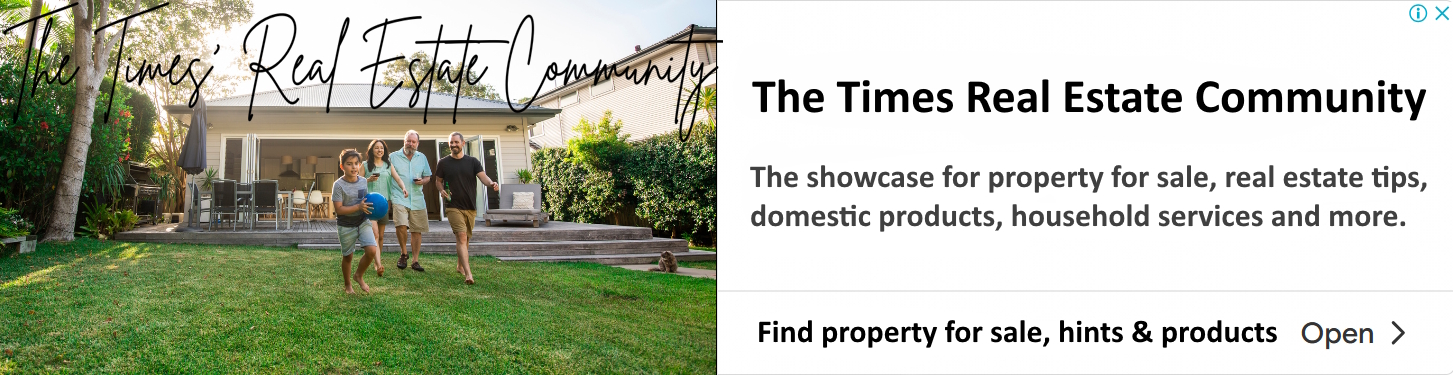Bukan solusi, evakuasi warga Gaza justru ancaman bagi masa depan Palestina
- Written by Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

● Evakuasi warga Gaza dapat memperkuat status pengungsian mereka secara permanen.
● Evakuasi juga bisa mengurangi tekanan terhadap Israel.
● Indonesia harus memastikan warga Gaza yang dievakuasi tetap dijamin hak untuk kembali.
Presiden Prabowo Subianto pada 9 April 2025 mengumumkan[1] rencana evakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia. Mereka yang akan dievakuasi adalah korban luka, anak-anak yatim piatu, dan warga sipil yang mengalami trauma akibat agresi Israel.
Pernyataan ini disampaikan langsung dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat sebelum Prabowo memulai kunjungan diplomatik ke lima negara Timur Tengah: Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Langkah ini langsung menjadi sorotan publik di Indonesia. Banyak masyarakat yang mendukung rencana tersebut, mengingat solidaritas terhadap rakyat Palestina memang mengakar kuat[2] di masyarakat Indonesia.
Di permukaan, evakuasi ini tampak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung Palestina[3]. Namun, dari perspektif politik dalam negeri, evakuasi ini sebenarnya bukanlah solusi permanen untuk membantu Palestina.
Justru, secara tidak sadar, langkah ini berpotensi melemahkan posisi warga Gaza dalam perjuangan atas hak dan tanah air mereka. Komunitas internasional bisa menganggap bahwa penduduk Gaza diselamatkan dan direlokasi, padahal sebenarnya mereka punya hak atas wilayahnya. Hal ini akan menguntungkan narasi Israel yang selama ini ingin mengosongkan Gaza dari warganya.
Bukan solusi permanen
Menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), evakuasi[4] adalah pemindahan sementara warga sipil dari daerah berbahaya ke tempat yang lebih aman. Evakuasi kemanusiaan merupakan bagian dari tanggap darurat konflik[5].
Namun, evakuasi hanya sah jika dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, dan tidak menghapus hak untuk kembali.
Hukum internasional[7] juga menegaskan bahwa evakuasi tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara pendudukan untuk melindungi warga sipil. Evakuasi adalah langkah terakhir[8], bukan pengganti resolusi politik.
Dalam konteks Gaza, jika tidak dibarengi kerangka jangka panjang dan jaminan pemulihan hak-hak rakyat Palestina, evakuasi bisa berubah menjadi solusi semu, bahkan memperkuat status pengungsian mereka secara permanen.
Jika tetap ingin mengevakuasi warga Gaza, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak melemahkan hak-hak dasar rakyat Palestina atas tanah air, termasuk hak untuk kembali, serta tetap mendorong penyelesaian politik yang adil.
Pergeseran dari ‘hak kembali’ menjadi ‘pemukiman ulang’
Resolusi Majelis Umum PBB 194[9] menegaskan bahwa pengungsi Palestina harus diizinkan kembali ke rumah mereka. Namun nyatanya, hingga tahun 2025, hak ini masih terus ditolak oleh Israel[10]. Faktanya, tidak ada satu pun[11] dari ratusan resolusi PBB yang menjamin hak kembali pengungsi Palestina yang pernah dilaksanakan.
Dengan membawa warga Gaza ke negara ketiga seperti Indonesia, ada risiko fokus dunia internasional yang bergeser. Dari “repatriasi” (pemulangan) menjadi “resettlement” (pemukiman ulang). Ini bertentangan dengan prinsip Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)[12] yang menekankan bahwa hak untuk kembali tidak boleh dikorbankan.
Pengosongan wilayah dari penduduk sipil—meski bersifat sementara—dapat menjadi dalih untuk perubahan demografi secara paksa. Ini bukan hal baru.
Pasca 1948 (Nakba)[14], jutaan warga Palestina terusir dari tanahnya. Hingga tahun 2023, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat[15] lebih dari lima juta pengungsi Palestina tersebar di kamp-kamp pengungsian tanpa kepastian kembali.
Selain itu, evakuasi juga bisa mengurangi tekanan terhadap Israel. Dengan warga sipil “diamankan” oleh negara-negara ketiga, negara pendukung Israel seperti Amerika Serikat (AS) dapat mengklaim bahwa masalah kemanusiaan telah tertangani, dan berdalih bahwa tidak ada lagi urgensi untuk menghentikan agresi militer atau mengadili pelanggaran hak asasi manusia.
Kepentingan moral atau politik?
Prabowo memang tengah berupaya membentuk citra global yang lebih “lunak” dan diplomatis[16]. Sebagai mantan jenderal, Prabowo kerap diasosiasikan dengan pendekatan militer. Misi evakuasi ini bisa menjadi langkah rebranding politik luar negeri Indonesia ke arah diplomasi dan soft power.
Namun, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel tidak sepenuhnya hitam-putih[17]. Walau tidak ada hubungan diplomatik resmi, kerja sama informal tetap berlangsung, terutama di bidang teknologi dan perdagangan.
Tanpa narasi politik yang konsisten dan tegas, evakuasi ini justru bisa melemahkan kredibilitas Indonesia di mata Global South[18]—kelompok negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang kebanyakan berada di belahan Bumi bagian selatan.
Indonesia harus belajar dari pengalaman
Indonesia masih mengalami dilema dalam menangani pengungsi Timur Tengah. Hingga akhir 2023, UNHCR mencatat[19] ada 12.295 pengungsi terdaftar di Indonesia. Mayoritas berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Irak.
Banyak dari mereka telah tinggal bertahun-tahun tanpa kepastian hukum, pendidikan, pekerjaan hingga layanan dasar lainnya.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang jelas, pengungsi bisa terjebak dalam ketidakpastian yang tidak manusiawi. Indonesia harus memastikan bahwa warga Gaza yang dievakuasi tidak mengalami hal serupa. Mereka harus tetap dijamin hak untuk kembali dan tidak “terperangkap” dalam sistem penampungan jangka panjang.
Evakuasi Gaza oleh Indonesia adalah tindakan yang mulia secara kemanusiaan. Namun dalam politik global, tindakan mulia bisa dimanipulasi jika tidak dibarengi kehati-hatian dan strategi.
Kebijakan Prabowo ini bisa menjadi titik awal dari babak baru dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia, tetapi berisiko menjadi bagian dari narasi yang justru menguntungkan Israel dan sekutu sebagai pelaku kekerasan.
Solidaritas bukan sekadar menyelamatkan korban. Solidaritas yang sesungguhnya adalah memastikan akar konflik diatasi dan hak rakyat Palestina dipulihkan, yaitu hak mereka atas tanah airnya.
References
- ^ mengumumkan (www.bbc.com)
- ^ mengakar kuat (journal.unair.ac.id)
- ^ konsisten mendukung Palestina (www.presidenri.go.id)
- ^ evakuasi (www.ifrc.org)
- ^ tanggap darurat konflik (yadda.icm.edu.pl)
- ^ Anas-Mohammed/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Hukum internasional (guide-humanitarian-law.org)
- ^ langkah terakhir (heinonline.org)
- ^ Resolusi Majelis Umum PBB 194 (www.unrwa.org)
- ^ terus ditolak oleh Israel (www.middleeasteye.net)
- ^ tidak ada satu pun (reliefweb.int)
- ^ prinsip Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) (www.unhcr.org)
- ^ Anas-Mohammed/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Pasca 1948 (Nakba) (books.google.co.id)
- ^ Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat (www.unrwa.org)
- ^ “lunak” dan diplomatis (theconversation.com)
- ^ tidak sepenuhnya hitam-putih (theconversation.com)
- ^ Global South (theconversation.com)
- ^ UNHCR mencatat (www.unhcr.org)
- ^ Donny Hery/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo