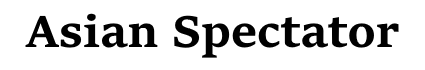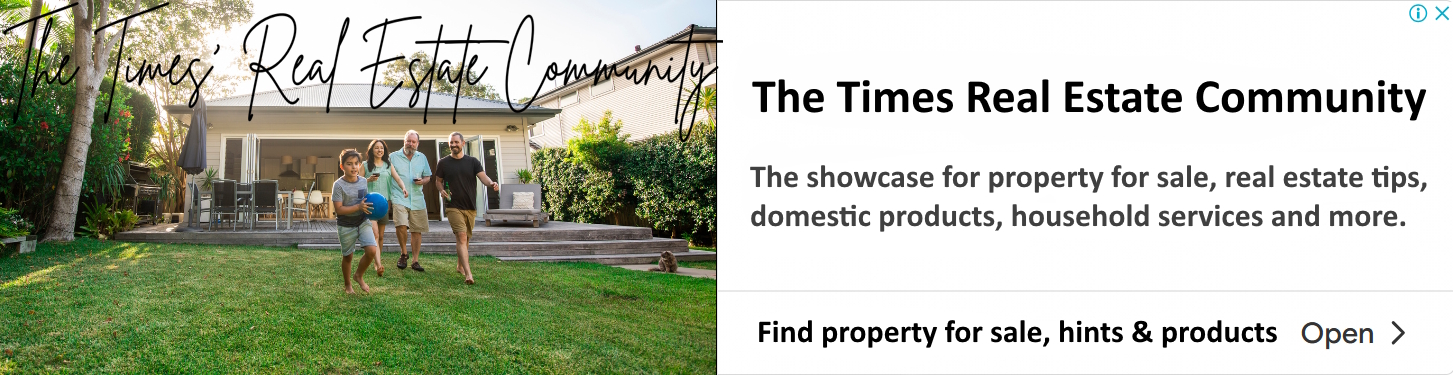Menjawab miskonsepsi tentang dekolonisasi sains : mengapa pembebasan riset dari dominasi Barat bukanlah sikap anti-ilmiah
- Written by Fajri Siregar, PhD Candidate, University of Amsterdam

Wacana “dekolonisasi sains[1]” makin berkembang di kalangan akademisi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membebaskan agenda riset mereka dari dominasi Barat (“eurosentrisme”).
Dalam artikel saya[2] di The Conversation Indonesia (TCID) awal tahun ini, saya menjelaskan bagaimana konsep ini penting bagi peneliti Indonesia, terutama di rumpun ilmu sosial, untuk melepaskan diri dari narasi ilmiah yang cenderung kolonialis. Ini juga jadi momen penting bagi mereka untuk mengangkat wawasan lokal ke dalam agenda riset.
Meski demikian, wacana dekolonisasi sains masih mendapat kritik dari beberapa peneliti.
Dalam salah satu artikel di TCID[3], misalnya, seorang rekan akademisi Indonesia melayangkan kritik terhadap analisis saya sebelumnya.
Sang penulis menjabarkan beberapa argumen utama: 1) wacana membebaskan sains dari dominasi Barat bisa memicu sikap anti-ilmiah, serta 2) dunia pendidikan dan kurikulum Indonesia mengadopsi sains yang berangkat dari tradisi lokal maupun budaya global sehingga tak serta merta eurosentris.
Bagi saya, tidak ada satu pun mazhab atau konsep yang perlu dibela secara mutlak, terlebih dalam ilmu sosial yang bergerak sangat cair. Dekolonisasi sains pun demikian.
Hanya saja, kita perlu pahami dulu mengapa gerakan dekolonisasi sains dianggap bermanfaat oleh pelaku sains[4], terutama mereka di negara berkembang dan yang berkutat dalam ilmu sosial.
Meski artikel sanggahan tersebut mengajukan kritik yang valid dan berguna untuk memperdalam diskusi, saya perlu menunjukkan satu-dua kekeliruan yang menyertai kritik tersebut.
Read more: Dekolonisasi sains: pentingnya memerdekakan ilmu pengetahuan dari ketergantungan pada dunia Barat[5]
Dekolonisasi tidak anti-sains
Satu kritik terhadap dekolonisasi sains berbunyi bahwa lepas dari pengaruh Barat[6] – sebagai penghasil teori sains utama di era modern – sama dengan menanggalkan prinsip sains dan metode ilmiah.
Saya ingin merespons ini dengan mengajak kita menyadari, sebagaimana telah disampaikan banyak akademisi, bahwa penyebaran sains secara global adalah efek samping dari penjajahan, kolonisalisme, dan imperialisme[7].
Hal ini mengakibatkan sains tersebut senantiasa erat dengan persoalan kuasa.
Di sini, dominasi negara imperialis kerap meminggirkan pemikiran alternatif dan konteks lokal. Pelaku sains non-Barat seakan hanya merupakan objek pengetahuan yang tak punya otoritas untuk menyelediki diri sendiri.
Sepanjang sejarah[8], alih-alih mendapat manfaat dari kolaborasi internasional, mereka sering berujung sekadar sebagai “pengamat”, “pembantu”[9], atau bahkan hanya dilibatkan dalam riset agar terlihat “inklusif” saja[10].
Di artikel saya sebelumnya, saya juga memberi contoh bagaimana watak kolonialis ini muncul – dari pandangan dalam ilmu sosial yang cenderung rasis dan menggambarkan orang non-kulit putih[11] sebagai pihak yang tidak cerdas, hingga penamaan fauna dan flora dalam riset biologi di Indonesia yang menyingkirkan wawasan suku-suku lokal[12].
Pada akhirnya, dekolonisasi sains bukanlah menolak metode ilmiah itu sendiri, melainkan mengajak untuk mempertanyakan sifat kolonialis yang terbawa dalam penyebaran sains dari negara Barat maupun kolaborasi ilmiah dengan negara berkembang.
Peran penting dekolonisasi dalam riset dan pendidikan tinggi
Kritik lain adalah anggapan bahwa sistem pendidikan yang berbasis sains modern, secara keseluruhan harus dirombak ulang hanya karena kita setuju dengan perspektif dekolonisasi.
Dalam artikel di atas yang mengkritik dekolonisasi, misalnya, sang penulis membela pendidikan di Indonesia.
Ia berargumen bahwa sistem pendidikan kita tidaklah didominasi Barat karena berakar pada tradisi sebelum masa kolonial (dari politik etis Belanda[13] hingga wawasan Ki Hajar Dewantara), serta mengadopsi budaya sains global (seperti matematika lintas era[14] termasuk zaman keemasan Islam[15], India, Cina dan Barat).
Menurut saya, kurikulum di jenjang sekolah sedikit berbeda konteks. Muatan pendidikan dari SD hingga SMA berbicara penyampaian sains dasar dan universal, yang memang perlu dipahami semua pelajar.
Dekolonisasi, di sisi lain, lebih menyangkut kurikulum di pendidikan tinggi yang mulai memasuki tataran pengetahuan yang lebih kritis.
Di dunia Barat seperti Inggris Raya (UK), berbagai kurikulum universitas mulai mengalami dekolonisasi[16] – misalnya dengan mendiversifikasi literatur[17] dari akademisi non-Barat hingga banyak memakai metode riset yang lebih mengangkat suara subjek dari negara dunia Selatan[18] – sebagai upaya menyeimbangkan perspektif sains dari berbagai budaya.
Ketika mereka mulai memberi ruang lebih besar pagi ilmuwan non-Barat dalam silabus mereka sendiri, mengapa kita tidak melihat relevansinya dengan kurikulum (pendidikan tinggi) di tanah air?
Dekolonisasi sains tidak pernah menganggap bahwa seluruh konten pendidikan yang selama ini kita kenal harus ditanggalkan, atau sains yang kita pelajari di sekolah seolah-olah tidak memiliki manfaat.
Pengusung dekolonisasi tetap memegang teguh prinsip sains sebagai landasan penting bagi semua pelajar dan peneliti.
Namun, di saat yang sama, pengusung dekolonisasi percaya bahwa nalar kritis kita bisa (dan harus) menggugat berbagai narasi sains yang tak selalu mencerminkan realita di masyarakat atau yang lahir dari kolonialisme – termasuk relasi kuasa dalam riset.
Ini mengapa dekolonisasi harus dipahami sebagai upaya yang sifatnya lebih dari sekadar ‘anti-Barat’.
Sekadar menyebutkan pengaruh sistem pendidikan abad terdahulu atau terjebak nostalgia sains yang berlandaskan identitas keagamaan atau sejarah masa lalu, tidaklah cukup.
Bahaya menganaktirikan pengetahuan yang bersumber dari konteks lokal
Selain itu, pengkritik dekolonisasi sains juga mempertanyakan sejauh mana batasan dari dekolonisasi.
Mereka bertanya[19], misalnya, apakah wacana dekolonisasi ini akan sampai menghapus dominasi Bahasa Indonesia dalam kurikulum yang “menjajah” bahasa daerah?
Jawaban singkatnya, ‘bisa’ – pelestarian bahasa lokal adalah salah satu cara. Namun, poin utamanya tak melulu tentang bahasa yang dipakai dalam pendidikan atau riset, melainkan bagaimana wawasan lokal atau peneliti lokal bisa mendapat porsi yang penting dalam khasanah pengetahuan dan sains.
Satu contoh yang cenderung sensitif namun bisa menjadi titik awal dekolonisasi pengetahuan di Indonesia adalah isu Papua.
Bagi banyak pihak, upaya untuk membicarakan Papua dengan melibatkan orang Papua tidak sering dilakukan karena terlampau politis[20]. Padahal, agenda dekolonisasi sains persis bermain di titik itu: berani mengakui bahwa sains sarat dengan kandungan politis dan narasi kolonial – termasuk kentalnya dominasi sejarah versi negara[21] yang menyingkirkan perspektif peneliti Papua.
Selain itu, semakin banyak kita bisa menyertakan studi atau riset lokal ke dalam silabus[22], semakin mudah mahasiswa merefleksikan bahan kuliah mereka dengan realita keseharian.
Kesadaran ini tidak hanya berlangsung dalam ilmu sosial. Seni pun, misalnya studi musik, semakin berupaya untuk menghapus dikotomi (pembedaan) antara “musik etnik” dan “musik modern”[23].
Untuk menyukseskan upaya ini, para peneliti dan dosen musik tak bisa hanya terus mempelajari ‘kanon klasik’ atau teori musik mainstream (arus utama). Jika mereka tak memperluas cakrawala ilmiah dengan mempelajari wawasan musik lokal, mereka akan senantiasa terjebak pada apa yang dianggap benar sejak era penjajahan.
Inilah tujuan awal dekolonisasi sains, agar pengetahuan lokal tidak ditempatkan lebih rendah dari teori besar ala Barat yang sering kita rujuk. Kita bisa memulai ini dengan memperbanyak arsip kita terlebih dahulu: mengajak ilmuwan di Indonesia untuk mempublikasikan riset yang mengandung wawasan lokal.
Berdasarkan studi sejarah[24], sosiologi[25], dan antropologi[26], pandangan sains yang eurosentris pun bisa berbahaya karena menutupi narasi lokal yang tidak pernah terangkat.
Sebagian besar pengurus Fakultas Ilmu Sosial di Indonesia yang saya ketahui juga belum menyadari betapa politisnya pengaruh literatur terhadap cakrawala mahasiswa. Cara berpikirnya masih terpaku pada apa yang dianggap ‘kanon klasik’ dan teori besar. Perspektif seperti ini sudah kedaluwarsa.
Dengan demikian, agenda dekolonisasi sains –- yang menurut saya masih sangat terbuka – mungkin hanya terlihat jelas bagi mereka yang bisa melihat bahwa pengetahuan ilmiah yang ada masih bias dan sangat terbatas.
References
- ^ dekolonisasi sains (theconversation.com)
- ^ artikel saya (theconversation.com)
- ^ salah satu artikel di TCID (theconversation.com)
- ^ dianggap bermanfaat oleh pelaku sains (www.wiley.com)
- ^ Dekolonisasi sains: pentingnya memerdekakan ilmu pengetahuan dari ketergantungan pada dunia Barat (theconversation.com)
- ^ pengaruh Barat (theconversation.com)
- ^ efek samping dari penjajahan, kolonisalisme, dan imperialisme (theconversation.com)
- ^ Sepanjang sejarah (theconversation.com)
- ^ “pengamat”, “pembantu” (theconversation.com)
- ^ terlihat “inklusif” saja (www.gicnetwork.be)
- ^ menggambarkan orang non-kulit putih (theconversation.com)
- ^ menyingkirkan wawasan suku-suku lokal (www.tandfonline.com)
- ^ politik etis Belanda (e-journal.unipma.ac.id)
- ^ matematika lintas era (www.degruyter.com)
- ^ zaman keemasan Islam (books.google.com.au)
- ^ mulai mengalami dekolonisasi (www.keele.ac.uk)
- ^ mendiversifikasi literatur (www.timeshighereducation.com)
- ^ mengangkat suara subjek dari negara dunia Selatan (sites.google.com)
- ^ Mereka bertanya (theconversation.com)
- ^ terlampau politis (papua.lipi.go.id)
- ^ dominasi sejarah versi negara (indoprogress.com)
- ^ menyertakan studi atau riset lokal ke dalam silabus (theconversation.com)
- ^ menghapus dikotomi (pembedaan) antara “musik etnik” dan “musik modern” (www.researchgate.net)
- ^ sejarah (www.scielo.org.za)
- ^ sosiologi (journals.sagepub.com)
- ^ antropologi (nycstandswithstandingrock.files.wordpress.com)
Authors: Fajri Siregar, PhD Candidate, University of Amsterdam