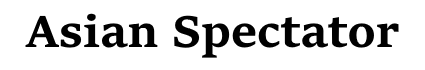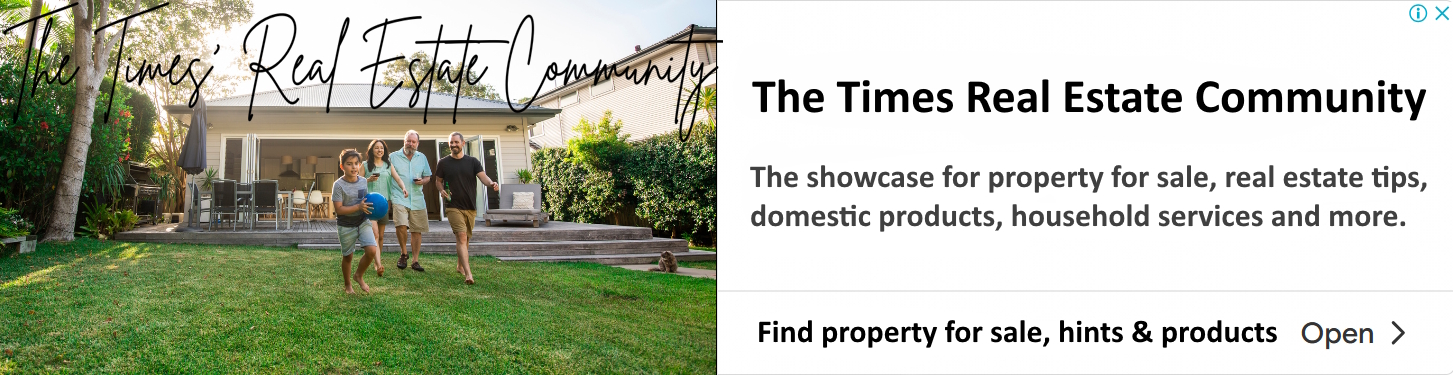20 tahun pasca-tsunami Aceh, kontribusi perempuan tak diakui, kebijakan daerah masih diskriminatif
- Written by Suraiya Kamaruzzaman, Dosen Fakultas Teknik / Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim USK, Universitas Syiah Kuala

Sebagai contoh, pada 2017, hanya ada satu wakil wali kota perempuan dari 23 kepala daerah kabupaten/kota. Hanya dua perempuan dari 65 pejabat eselon dua di Aceh.
Jika dibandingkan dengan kontribusi perempuan selama dan pasca-perang dan tsunami, keterbatasan ruang bagi perempuan dalam posisi-posisi pengambil kebijakan sangat tidak adil.
Selain itu, perempuan Aceh masih sering terdiskriminasi oleh kebijakan patriarkis yang kuat yang berlaku di berbagai kabupaten/kota dan provinsi. Ada yang berupa qanun (peraturan daerah), peraturan bupati/wali kota, surat edaran, dan lainnya.
Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 5 Tahun 2010[5] tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam, misalnya, mengatur tentang pemakaian busana Islam di Aceh Barat. Aturan ini melarang[6] perempuan mengenakan celana panjang dalam aktivitas sehari-hari, meskipun pakaian tradisional perempuan Aceh pun menggunakan celana panjang.
Salah satu konsekuensi adanya larangan ini adalah pemeriksaan pakaian perempuan[7] di area publik dan pembagian 20 ribu rok. Jika tidak menggunakan rok, maka perempuan tidak akan mendapatkan pelayanan publik[8].
Di Lhokseumawe, pada Januari 2013, pemerintah kota mengeluarkan Surat Edaran[9] yang mewajibkan perempuan untuk duduk menyamping[10] di kendaraan bermotor sebagai penumpang. Padahal, duduk menyamping pada kendaraan bermotor memperbesar risiko kecelakaan[11].
Di Bireuen pada Agustus 2018, Bupati setempat menerbitkan Surat Edaran[12] mengenai standar kafe dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam. Edaran tersebut melarang[13] karyawan kafe untuk melayani perempuan setelah pukul 21:00 jika tanpa mahram serta melarang perempuan duduk di meja yang sama dengan laki-laki yang bukan mahram.
Kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut memperkuat budaya patriarki sekaligus memperburuk posisi perempuan dalam masyarakat.
Kekerasan terhadap perempuan juga masih sangat rentan terjadi di Aceh. Antara tahun 2019 dan 2023, tercatat sebanyak 5.020 laporan[14] kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan angka yang terus meningkat setiap tahun. Provinsi Aceh pun menempati peringkat teratas[15] dalam kasus perkosaan.
Di tengah situasi tersebut, alokasi anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) hanya mencapai 0,12% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada periode 2020 hingga 2024. Meski meningkat, dana tersebut sering kali tidak cukup[16] untuk menjawab kebutuhan nyata perempuan, terutama perempuan yang menjadi korban konflik.
Perempuan muda: Harapan dan tantangan baru
Perempuan muda, terutama generasi Z (Gen-Z), menghadapi tantangan besar, terutama dalam upaya mendobrak budaya yang masih sangat patriarki guna memajukan pendidikan bagi perempuan.
Kabar baiknya, kehadiran perempuan muda membawa harapan baru dalam proses perdamaian dan pemberdayaan perempuan. Mereka lebih terhubung ke seluruh dunia melalui jaringan internet, sehingga memungkinkannya untuk berbicara tentang hak-hak perempuan secara lebih terbuka.
Perempuan muda memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak perubahan, dengan menantang norma-norma yang ada dan memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang-ruang publik. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menyuarakan hak-hak perempuan di media sosial.
Untuk memastikan bahwa perempuan di Aceh dapat menikmati perdamaian secara substansial, pemerintah dan masyarakat harus melakukan tindakan nyata. Perempuan harus dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perdamaian dan pemulihan pascakonflik. Pemerintah Aceh perlu lebih mendukung kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik dan pemerintahan.
Salah satu perubahan yang sangat diperlukan adalah pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks Qanun Jinayah (hukum pidana Aceh).
Hukum Aceh saat ini masih belum memberikan perlindungan yang optimal dan pemulihan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Malah masih ada pihak-pihak yang menyalahkan korban dan menambah beban bagi mereka.
Aceh mempunyai kebutuhan besar untuk melindungi hak perempuan korban kekerasan seksual, dan memperkuat sistem hukum yang lebih menguntungkan korban. Pemerintah juga harus menghapuskan kebijakan diskriminatif yang masih ada.
Mari kita pastikan bahwa suara perempuan Aceh didengar dan peran mereka dihargai, bukan hanya sebagai pengingat masa lalu, tetapi sebagai agen perubahan untuk membawa Aceh menuju perdamaian yang sebenarnya.
References
- ^ Perjanjian Damai Helsinki (journal2.um.ac.id)
- ^ 2000 perempuan (womenandcve.id)
- ^ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (dinaspppa.acehprov.go.id)
- ^ Zulhidayat AY/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 5 Tahun 2010 (www.google.com)
- ^ melarang (www.nu.or.id)
- ^ pemeriksaan pakaian perempuan (surabaya.tribunnews.com)
- ^ tidak akan mendapatkan pelayanan publik (www.tribunnews.com)
- ^ Surat Edaran (nasional.kompas.com)
- ^ duduk menyamping (www.bbc.com)
- ^ memperbesar risiko kecelakaan (otomotif.kompas.com)
- ^ Surat Edaran (www.tempo.co)
- ^ melarang (news.okezone.com)
- ^ 5.020 laporan (www.kompas.com)
- ^ peringkat teratas (www.tempo.co)
- ^ tidak cukup (www.rmolaceh.id)
- ^ DANIEL SUPRIYONO/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Suraiya Kamaruzzaman, Dosen Fakultas Teknik / Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim USK, Universitas Syiah Kuala