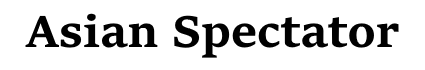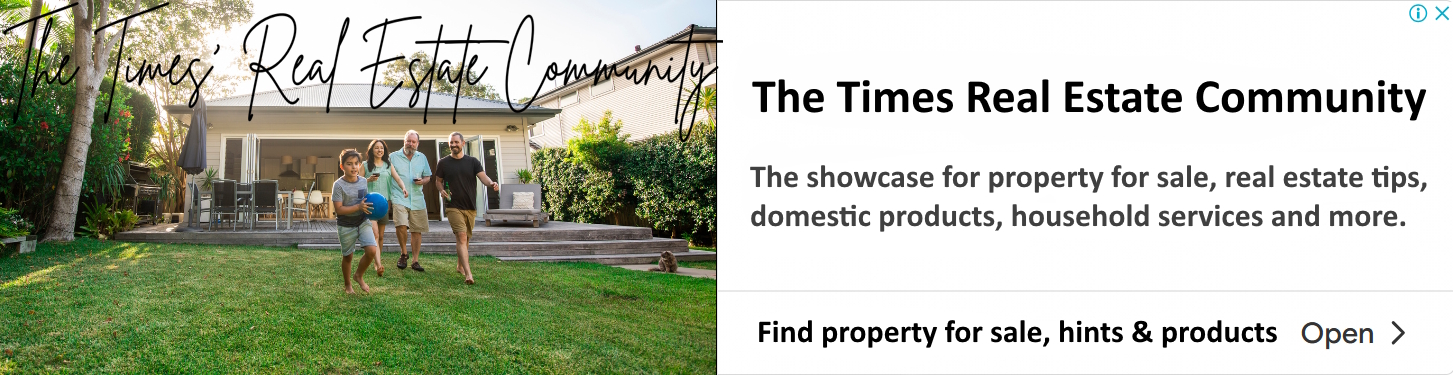Pembangunan infrastruktur dan hilirisasi Prabowo: Akankah partisipasi masyarakat lokal diabaikan lagi?
- Written by Ani Nur Mujahidah Rasunnah, Researcher, Nalar Institute

Evaluasi mendasar atas implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) selama satu dekade pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo adalah pengabaian keterlibatan masyarakat terdampak[1] dalam proses kebijakan.
Sebagai contoh, di Sorong, Papua Barat, warga lokal tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah[2] mengenai tujuan dan manfaat dibangunnya proyek Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Sorong (KEK Sorong). Sementara masyarakat adat Poco Leok yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi berakhir dikriminalisasi[3].
Studi[4] yang dilakukan Nalar Institute pada 2024 mengungkap adanya korelasi antara minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dengan menurunnya kesejahteraan warga.
Selain pembangunan KEK Sorong, PLTP Poco Leok[5], Food Estate di Kalimantan Tengah[6], sentra Nikel di Pulau Obi[7], dan Smelter Konawe[8] adalah beberapa dari sekian banyak PSN yang dibangun tanpa sosialisasi publik. Akibatnya, lahan produktif raib, warga kehilangan mata pencaharian utama, pendapatan masyarakat berkurang, dan persentase penduduk miskin meningkat[9] di kawasan pertambangan Nikel.
Pembangunan di era pemerintahan Jokowi yang minim partisipasi warga, menunjukkan pola yang mirip–jika tidak bisa dikatakan sama persis–dengan pemerintahan Orde Baru, di mana negara menjadi aktor utama[10] yang memegang kendali penuh dalam proses kebijakan. Segala bentuk tindakan yang diinisiasi pemerintah mendapat legitimisasi, termasuk menggunakan cara koersif jika diperlukan untuk menjaga kestabilan, kepatuhan, dan demi tercapainya tujuan pembangunan.
Target ambisius Prabowo
Target pemerintahan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan perkara mudah. Untuk meraih ambisi tersebut, hilirisasi nonmineral[11] dan industrialisasi[12] menjadi salah satu kebijakan kunci sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita.
Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8%[13], yakni pada masa Orde Baru ketika pemerintah, yang saat itu dipimpin oleh Suharto, mantan mertua Prabowo, menerapkan pendekatan sentralistik.
Namun, capaian tersebut tidak berkelanjutan, mewariskan kerusakan alam[14], dan berakhir krisis pada tahun 1998. Oleh karenanya, pemerintahan Prabowo perlu pendekatan pembangunan yang partisipatif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh dalam jangka panjang.
Setidaknya ada tiga cara pendekatan yang perlu diterapkan pemerintah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi yang lebih inklusif dan partisipatif, yaitu: menghargai pengetahuan lokal, mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, dan meminta persetujuan masyarakat adat.
1. Menghargai pengetahuan lokal
Pembangunan dengan pendekatan partisipatif senantiasa menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma[15] mendasar bagi pembuat kebijakan, dengan mengakui bahwa masyarakat lokal/adat memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka, komunitas, dan lingkungan di wilayahnya.
Sebagai contoh, Suku Dayak yang bertempat di Kalimantan Tengah telah menerapkan sistem pertanian tradisional gilir balik (ladang berotasi)[16] selama ratusan tahun. Namun, ketika proyek food estate padi berlangsung di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, petani Suku Dayak kesulitan mengadopsi sistem tani sawah yang biasa dilakukan masyarakat Jawa.
Penerapan metode pertanian baru[17] juga dilakukan tanpa pendampingan dari dinas pertanian setempat. Alhasil, lahan seluas puluhan ribu hektare terbengkalai. Sebagian lahan malah berubah menjadi perkebunan sawit[18].
Apabila pemerintah ingin memaksimalkan produksi pertanian, proyek food estate perlu menerapkan teknik penanaman yang sesuai kultur dan tradisi masyarakat lokal. Oleh karena itu, kajian saintifik mendalam perlu dilakukan di tahap paling awal sebelum implementasi proyek, untuk memetakan tidak hanya kondisi alam tetapi juga sosial-budaya masyarakat setempat.
2. Mempertimbangkan aspek kebermanfaatan
Pembangunan yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan warga seharusnya menawarkan solusi yang selaras dengan kebutuhan dan isu relevan. Selama ini, infrastruktur yang dibangun alih-alih menjawab kebutuhan dasar, pemerintah kerap memprioritaskan pembangunan proyek kawasan industri besar atau pariwisata demi mendongkrak investasi, tetapi ekonomi warga perlahan dibiarkan mati.
Untuk itu, guna menghasilkan solusi yang selaras dengan isu aktual di lapangan, ada dua cara yang perlu dilakukan pemerintah:
Pertama, mempertimbangkan aspek kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, dalam rangka mengatasi krisis pangan di suatu daerah yang makanan pokok utamanya adalah sagu, memperbanyak perkebunan sagu lebih mungkin dibutuhkan masyarakat, daripada memperluas lahan pertanian padi atau jagung. Solusi terhadap persoalan pangan yang mengabaikan tradisi makanan pokok lokal hanya akan memperburuk kondisi kerentanan dan meningkatkan risiko bencana kelaparan[19].
Kedua, membuka ruang dialog aktif antara warga, pemerintah, dan perusahaan. Dalam pembangunan yang partisipatif, seluruh masyarakat terdampak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah maupun perusahaan juga mesti transparan terkait tujuan proyek dan hasil uji kelayakan lingkungan. Dengan begitu, publik bisa menimbang manfaat yang mereka terima dan mengukur kerugian imbas dari pembangunan proyek.
3. Mendapat persetujuan masyarakat adat
Setelah masyarakat menilai kerugian dan manfaat proyek, pembuat kebijakan perlu menghargai keputusan kolektif warga. Tetapi realitasnya, berbagai bentuk intimidasi[20] dan upaya kriminalisasi[21] kerap digunakan pemerintah maupun perusahaan untuk menekan protes dan aksi penolakan. Untuk itu, perlu ada kepastian hukum yang dapat melindungi dan mendukung hak warga, terutama hak masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak pembangunan.
Dalam deklarasi PBB dan konvensi internasional, sudah ada konsep Free, Prior and Informed Consent[22] (FPCI). Pada dasarnya, FPCI mengandung prinsip HAM yang menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sayangnya, Indonesia belum mengadopsi[23] 15 prinsip FPCI dalam aturan negara.
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sebenarnya dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan prinsip FPCI. Kendati demikian, pengesahan RUU MHA terus tertunda bertahun-tahun.
Mengingat urgensinya sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat adat, RUU MHA perlu segera disahkan oleh DPR. Dengan begitu, masyarakat adat memiliki payung hukum yang kuat dalam upaya melindungi budaya serta wilayahnya dari pembangunan yang eksploitatif.
Pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan, senantiasa mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya, jika cara-cara kekerasan lebih diutamakan ketimbang partisipasi bermakna, maka orientasi pembangunan besar kemungkinan tidak untuk kebermanfaatan publik secara luas, tetapi untuk segelintir kepentingan.
References
- ^ pengabaian keterlibatan masyarakat terdampak (nalarinstitute.com)
- ^ tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah (aji.or.id)
- ^ berakhir dikriminalisasi (www.tempo.co)
- ^ Studi (nalarinstitute.com)
- ^ PLTP Poco Leok (betahita.id)
- ^ Food Estate di Kalimantan Tengah (pantaugambut.id)
- ^ sentra Nikel di Pulau Obi (mediaindonesia.com)
- ^ Smelter Konawe (projectmultatuli.org)
- ^ persentase penduduk miskin meningkat (www.kompas.id)
- ^ aktor utama (e-journal.unair.ac.id)
- ^ hilirisasi nonmineral (www.tempo.co)
- ^ industrialisasi (va.medcom.id)
- ^ di atas 8% (www.cnnindonesia.com)
- ^ mewariskan kerusakan alam (fwi.or.id)
- ^ perubahan paradigma (press-files.anu.edu.au)
- ^ gilir balik (ladang berotasi) (www.kompas.id)
- ^ Penerapan metode pertanian baru (www.bbc.com)
- ^ berubah menjadi perkebunan sawit (www.tempo.co)
- ^ risiko bencana kelaparan (www.kompas.id)
- ^ bentuk intimidasi (www.ekuatorial.com)
- ^ upaya kriminalisasi (www.tempo.co)
- ^ Free, Prior and Informed Consent (www.un.org)
- ^ belum mengadopsi (theconversation.com)
Authors: Ani Nur Mujahidah Rasunnah, Researcher, Nalar Institute