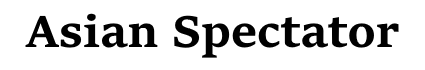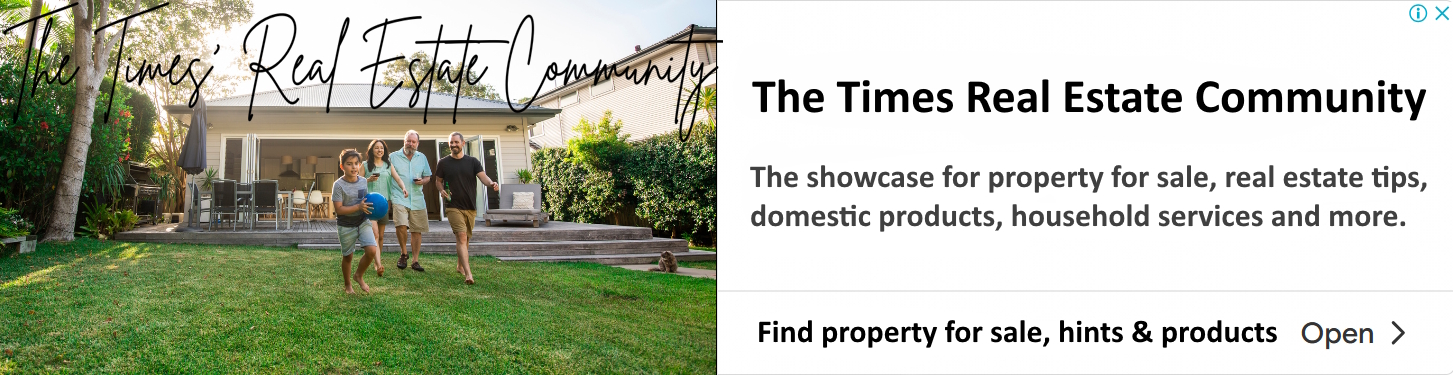#IndonesiaGelap: Alarm bagi publik agar tak terlena narasi penguasa
- Written by Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

Bermula dari media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi bentuk aksi kolektif masyarakat, utamanya kaum muda, yang menuntut keadilan terhadap pemerintah hari ini.
Aksi kolektif yang berawal dari tagar tersebut terealisasi secara serentak di berbagai kota oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka menuntut pertanggungjawaban[1] atas segala bentuk kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak prorakyat.
Bukan hanya untuk memprotes pemerintah, hadirnya #IndonesiaGelap juga terlihat menjadi narasi perlawanan di tengah dominasi penguasa yang menyebarkan narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Penguasa dalam hal ini pemerintah, kerap menghadirkan gambaran bahwa kondisi Indonesia baik-baik saja[2]. Selain itu, media arus utama juga dapat memperburuk situasi dengan terus menerus menggambarkan kondisi yang tidak sesuai realitas.
Aksi kolektif seperti #IndonesiaGelap menjadi pengingat atau alarm bagi masyarakat luas bahwa ada realitas lain yang coba disembunyikan oleh penguasa. Publik jangan sampai terlena oleh realitas palsu pemerintah.
Terlena narasi penguasa
Berdasarkan hasil survei opini publik oleh Litbang Kompas[3] pada 4-10 Januari 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. Hanya 19,1% menyatakan tidak puas.
Ini sebenarnya perlu dipahami lebih kritis, karena data tersebut bisa saja hanya respons dari masyarakat yang menjadi korban dari narasi penguasa.
Selain itu, kita perlu juga mempertanyakan metode dan interpretasi survei itu sendiri. Dalam The Illusion of Public Opinion: Fact and Artifact in American Public Opinion Polls (2004)[4], George F. Bishop menyoroti bagaimana desain pertanyaan dalam survei dapat memengaruhi hasil yang diinginkan.
Misalnya, jika survei menanyakan kepuasan secara umum tanpa merinci aspek spesifik dari kebijakan pemerintah, maka responden mungkin akan memberikan jawaban yang lebih positif. Sebab, mereka tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan aspek negatif secara mendalam.
Temuan akan kepuasan semacam itu bisa dilihat juga melalui pendekatan System Justification Theory oleh Jost dan Banaji pada 1994[5]. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk membenarkan dan mempertahankan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada, meskipun sistem tersebut merugikan mereka.
John Jost[6], psikolog sosial Amerika Serikat mengembangkan teori tersebut lebih jauh dengan menunjukkan bahwa seseorang sering kali mendukung sistem yang ada bukan karena mereka mendapat manfaat langsung, tetapi karena adanya kebutuhan psikologis akan stabilitas, ketertiban, dan kepastian.
Sesuai dengan teori tersebut, dalam sistem politik, individu cenderung menerima narasi dominan yang disebarluaskan oleh penguasa dan media. Inipun termasuk apabila narasi tersebut bertentangan dengan kepentingan mereka
Itulah mengapa penguasa kita gemar menggunakan kerja dari para buzzer untuk membingkai sebuah peristiwa atau fenomena[7]. Semua itu dapat menguatkan narasi penguasa yang menjelaskan bahwa semua baik-baik saja.
Dalam buku The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion[8], psikolog sosial asal AS Jonathan Haidt menjelaskan bahwa preferensi politik masyarakat sering kali didasarkan pada emosi dan identitas kelompok, bukan analisis rasional terhadap kebijakan.
Jika pemerintah berhasil membangun citra populis yang kuat—misalnya dengan menampilkan diri sebagai pembela rakyat kecil atau pemimpin yang tegas—maka dukungan publik bisa meningkat. Ini bahkan jika kebijakan yang diambil justru merugikan mereka dalam jangka panjang.
Kuatnya narasi penguasa ini kerap kali diperparah oleh peran media massa yang melakukan propaganda model. Menurut Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988)[9], propaganda model adalah ketika kebijakan pemerintah dapat terlihat lebih populer dari kenyataan sesungguhnya karena adanya kontrol terhadap wacana publik.
Media yang berpihak pada elite politik[10] cenderung menonjolkan aspek positif pemerintahan. Sementara itu, kritik dibungkam atau disisihkan ke ruang-ruang marjinal.
Jika pemerintah terus menutup diri terhadap kritik dan mengandalkan strategi komunikasi hegemonik untuk menutupi kegagalannya, maka gerakan seperti #IndonesiaGelap akan semakin relevan sebagai ruang alternatif bagi warga untuk menuntut akuntabilitas.
Harapannya, gerakan ini tidak hanya menjadi reaksi sesaat terhadap kebijakan yang dinilai merugikan, tetapi berkembang menjadi upaya jangka panjang dalam membangun masyarakat sipil yang lebih kuat dan independen.
Merebut ruang narasi
Tantangan terbesar dari gerakan ini adalah bagaimana ia dapat bertahan dan berkembang di tengah represi politik dan kontrol terhadap ruang publik, serta dapat diakomodasi dalam kebijakan publik.
Pemerintah yang memiliki akses terhadap aparat, media, dan infrastruktur digital bisa berisiko menekan gerakan semacam ini melalui propaganda, kriminalisasi aktivis, atau bahkan sensor terhadap informasi kritis.
Oleh karena itu, aksi Indonesia Gelap harus mampu beradaptasi dengan strategi perlawanan yang fleksibel, mulai dari memperkuat jejaring solidaritas lintas sektor, menciptakan narasi tandingan yang lebih luas, hingga menggunakan teknologi untuk menghindari sensor dan manipulasi informasi. Jika tidak, gerakan ini berisiko meredup dan kehilangan daya dorongnya, seperti banyak gerakan protes lainnya yang gagal melewati fase awal euforia.
Ke depan, Indonesia Gelap harus lebih dari sekadar tagar dan aksi sesaat. Gerakan ini perlu bertransformasi menjadi ruang-ruang yang lebih terstruktur untuk edukasi politik dan mobilisasi massa yang berkelanjutan.
Kritik terhadap pemerintah juga harus diiringi dengan penyampaian solusi alternatif yang konkret. Harapannya, gerakan ini tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun kesadaran politik yang lebih mendalam.
Dengan menggabungkan kekuatan media sosial, aksi massa, dan kajian kritis terhadap kebijakan publik, gerakan ini bisa menjadi titik balik dalam mendorong demokrasi yang lebih substansial. Hanya dengan cara itu, Indonesia Gelap bisa benar-benar menjadi harapan bagi masyarakat yang ingin keluar dari kegelapan sistem politik yang manipulatif dan menindas.
References
- ^ menuntut pertanggungjawaban (www.tempo.co)
- ^ kondisi Indonesia baik-baik saja (www.cnnindonesia.com)
- ^ survei opini publik oleh Litbang Kompas (www.kompas.id)
- ^ The Illusion of Public Opinion: Fact and Artifact in American Public Opinion Polls (2004) (www.cambridge.org)
- ^ System Justification Theory oleh Jost dan Banaji pada 1994 (bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com)
- ^ John Jost (www.sciencedirect.com)
- ^ untuk membingkai sebuah peristiwa atau fenomena (ppim.uinjkt.ac.id)
- ^ The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion (www.goodreads.com)
- ^ Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988) (books.google.com)
- ^ berpihak pada elite politik (rowman.com)
Authors: Wawan Kurniawan, Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
Read more https://theconversation.com/indonesiagelap-alarm-bagi-publik-agar-tak-terlena-narasi-penguasa-250274