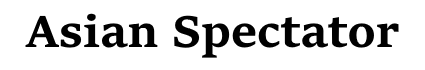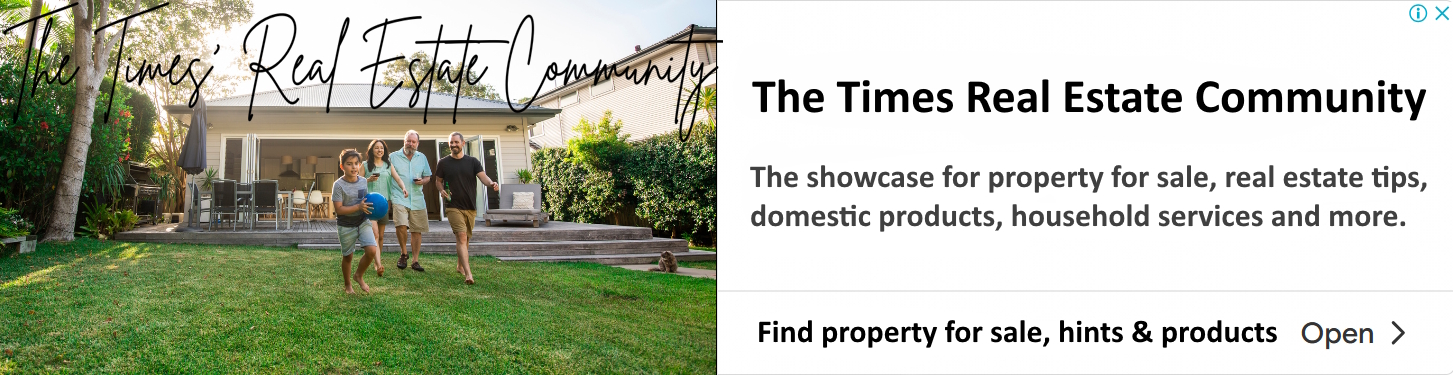Menjaga hasrat materialistis dan ‘flexing’ di media sosial lewat ‘mindfulness’
- Written by Cleoputri Yusainy, Associate Professor in General and Experimental Psychology, Universitas Brawijaya

● Instagram jadi ladang subur bagi budaya pamer.
● Keinginan untuk memiliki sesuatu sering kali dipicu oleh orang lain.
● ‘Mindfulness’ bisa menjadi rem di tengah dorongan konsumtif yang kian masif.
Notifikasi smartphone-mu berdenting. Influencer yang kamu ikuti baru saja mengunggah postingan di Instagram. Ketika membukanya, mungkin kamu akan mendapati mereka tengah berlibur ke luar negeri, berolahraga dengan sepeda yang harganya bisa di atas sebuah motor, menikmati perawatan tubuh mewah atau berganti iPhone yang baru saja rilis.
Ketika kamu berselancar di laman muka Instagrammu, algoritma pun bisa mengarahkan ke postingan serupa dari influenser yang tidak kamu ikuti.
Konsumerisme, materialisme, serta hedonisme yang terus tersaji melalui jejaring media sosial menciptakan budaya konsumsi yang jauh melampaui batas kemampuan alam untuk melakukan pembaruan. Praktik ‘flexing’, pamer keleluasaan untuk “membuang-buang” barang, jasa, dan waktu luang yang tidak dimiliki kebanyakan orang, dengan mudah tersua di penjuru platform Instagram.
Melibatkan 2.296 responden, riset kami[1] menyelidiki sejauh mana paparan pamer konsumtif dapat merangsang aspirasi materialistis pengguna Instagram, serta bagaimana efek ini dimediasi oleh antisipasi keterlibatan pengguna lain (anticipated engagement) dan dimoderasi oleh kesadaran lengkap (mindfulness) yang dimiliki audiens.
Mengenal hasrat dan keinginan meniru
Aspirasi materialistis[2] bermula dari hasrat. Nyaris tidak ada bentuk kesadaran yang bebas dari hasrat: dorongan yang mengawali pikiran, perilaku, dan ucapan. Hasrat merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam melakoni kehidupan kita sebagai manusia.
Hasrat menempatkan dirinya dalam segi bersudut tiga. Pertama, sudut kekayaan. Bekerja bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan, namun juga menimbun kebendaan. Semakin banyak hasil timbunan, semakin menggembirakan. Ironi lahir kemudian: semakin punya, justru semakin merasa papa.
Hasrat kedua adalah ketenaran. Hasrat ini mendorong untuk menaiki tangga sosial. Semakin banyak orang yang mengenali siapa kamu, semakin tinggi status sosial dan pengaruhmu. Tentu, ada konsekuensi. Ketika segala hal dipaparkan ke publik untuk mencari validasi, tidak ada lagi yang tersisa untuk diri sendiri.
Ketiga, hasrat pencitraan. Hasrat ini berpusat pada cerita tentang kebaikan, keunggulan kita dibanding orang lain, dan narasi keunikan kita. Sudut ini lebih murah ketimbang dua hasrat lainnya. Alih-alih melakukan kebajikan karena ketulusan, pujian terhadap citra diri menjadi tujuan akhirnya. Ketidaktulusan membuat kita selalu curiga, tindakan orang lain juga menyimpan motif tersembunyi.
References
- ^ riset kami (www.tandfonline.com)
- ^ Aspirasi materialistis (doi.org)
- ^ René Girard (1966) (www.press.jhu.edu)
- ^ atensi kolektif (arxiv.org)
- ^ Studi kami (doi.org)
- ^ mental (doi.org)
- ^ sosial (doi.org)
- ^ lingkungan (doi.org)
- ^ Riset kami (doi.org)
- ^ Timur (doi.org)
- ^ bersifat sementara (link.springer.com)
Authors: Cleoputri Yusainy, Associate Professor in General and Experimental Psychology, Universitas Brawijaya