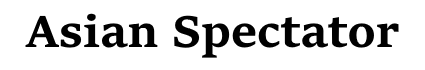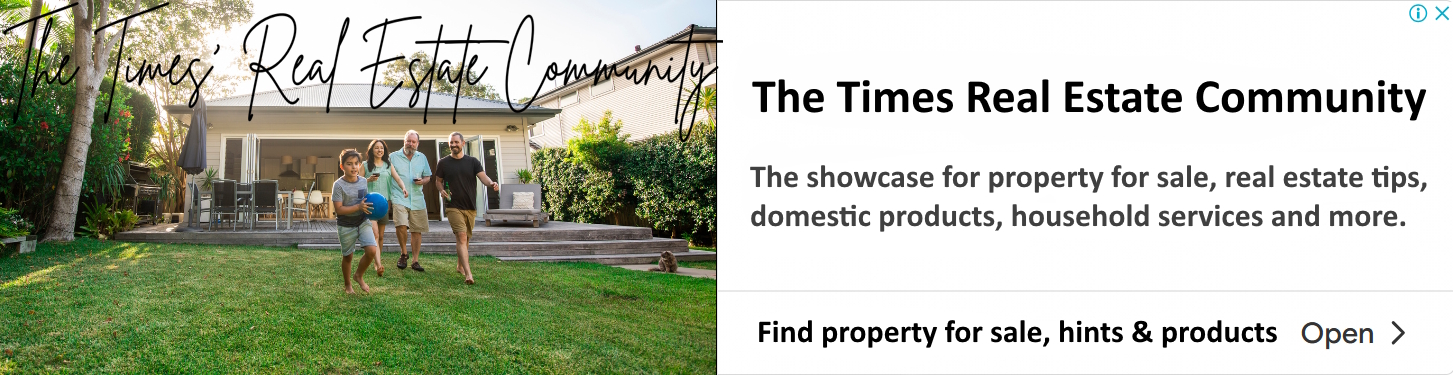Malas di dunia kerja tak selamanya buruk—mari keluar dari ekspektasi yang muluk-muluk
- Written by Katrien Devolder, Director of Public Philosophy, Professor of Applied Ethics, University of Oxford

Sebagai anak muda, kamu mungkin pernah disebut pemalas oleh generasi yang lebih senior. Kadang, kita jadi berpikir, mungkin kita memang pemalas. Akhirnya kita merasa bersalah saat sedang tak produktif. Bahkan berpura-pura produktif agar tak dikira malas.
Tenang, kamu tak sendirian. Meragukan produktivitas diri sendiri merupakan produk dari sistem kerja zaman sekarang. Ini adalah era kita dianggap harus terus-menerus mengejar dan mencapai sesuatu. Semakin banyak orang[1] menganggap Gen Z (dan Milenial) adalah generasi “pemalas” dan “banyak menuntut”. Hasilnya, kita merasa bahwa kita memang pemalas.
Di era saat ini yang memungkinkan kita bekerja dari rumah (work from home), makin sulit rasanya menyingkirkan perasaan bersalah karena tidak “produktif”. Artikel-artikel dengan judul Am I Depressed or Lazy?[2] (Apakah Aku Depresi atau Sekadar Malas?) menunjukkan bahwa banyak orang khawatir dicap malas, termasuk bagi orang yang dianggap “anak emas”[3].
Kemalasan tak bisa dilihat dari sisi individu saja, tapi juga dari sisi moral. Di berbagai budaya, kemalasan dianggap sebagai “kejelekan”, terbukti pula dari kitab agama-agama yang dikenal luas[4]. Maka dari itu, disebut “pemalas” terasa jauh lebih buruk dibanding disebut “sulit fokus” atau “lamban”. Ini karena secara moral, “pemalas” adalah karakter yang tercela.
Sayangnya, melabel seseorang (atau diri sendiri) sebagai seorang pemalas justru makin menumbuhkan mitos kerja yang berbahaya[5]. Mitos ini lahir dari etika kerja Protestan[6] (Protestant work ethic/PWE) yaitu pandangan bahwa kesuksesan sepenuhnya bergantung pada kerja keras individu. Makin kerja keras, makin hemat, maka bisa sukses.
Pandangan ini dimanfaatkan oleh sistem kapitalis yang menanamkan kepercayaan: satu-satunya jalan untuk menjadi sosok yang ideal dengan pencapaian membanggakan adalah dengan menjadi produktif tanpa henti.
Mitos tersebut menyuburkan budaya kerja yang menuntut seseorang harus bekerja lebih keras nonstop. Dampaknya adalah kecemasan, kelelahan mental[7] (burnout). Budaya ini juga rentan mendiskriminasi pada orang dengan gaya kerja berbeda atau orang yang tak mampu mengikuti ritme gila kerja tersebut.
Dampak mitos “pemalas” ini berbeda-beda bagi tiap individu. Jika kamu berasal dari suku tertentu, punya kondisi kesehatan kronis, tak punya tempat tinggal atau pekerjaan—kamu lebih rentan dicap “pemalas”.
Sebuah penelitian[8] menunjukkan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas lebih sering dianggap pemalas di sekolah. Mereka lebih sering dihukum daripada dibantu.
Karyawan dengan kondisi obesitas juga ditemukan lebih jarang mendapatkan promosi[9] atau kenaikan jabatan dalam pekerjaan karena dianggap “malas”. Orang-orang yang tak bisa melakukan pekerjaan ekstra karena harus merawat orang lain (misalnya pulang “tenggo” atau tepat waktu karena harus merawat lansia) pun sering dianggap tak cukup berkomitmen kerja sehingga tak menerima peluang perkembangan karier.
Apakah kita benar-benar malas?
Melabel seseorang sebagai “pemalas” merupakan tuduhan serius. Maka dari itu, kita perlu benar-benar memahami apa itu kemalasan.
Kalimat “kamu pemalas”, biasanya memiliki makna tersembunyi: “Kamu bisa meraih lebih banyak hal jika bekerja lebih keras”.
Anggaplah kita memang bisa meraih lebih banyak hal jika kita totalitas. Namun, apakah kita selalu totalitas di tiap hal? Pastinya tidak selalu.
Dengan begitu, apakah berarti kita sebenarnya pemalas, karena tak selalu totalitas?
Riset yang saya lakukan bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan ulang “kemalasan”. Saya mengeksplorasi bagaimana orang-orang memahami kemalasan, lalu menggunakan analisis filosofis untuk menemukan pemahaman sehari-hari yang paling masuk akal.
Dalam melakukan penelitian tersebut, saya menggabungkan berbagai area filosofi untuk membahas nilai dari usaha, kebajikan, dan sejauh mana kita bisa menyalahkan diri sendiri ketika tak bisa melakukan sesuatu karena tak punya cukup kemauan.
Analisis saya mengungkap[10] bahwa poin penting dari kemalasan adalah absennya alasan kuat (justifikasi) untuk tidak berupaya lebih keras sehingga membatasi usaha kita.
Coba pikirkan beberapa skenario ini:
- Kamu bekerja di bawah standar pekerjaanmu karena kamu tidak ingin repot,
- Kamu bersantai di akhir pekan sehingga bisa siap menghadapi minggu selanjutnya,
- Kamu membatasi upayamu karena harus jaga kesehatan akibat kondisi kesehatan kronis.
Pemahaman saya, hanya skenario pertama yang menunjukkan kemalasan.
Skenario lain justru menunjukkan kemalasan merupakan manajemen pengaturan kerja yang memiliki dasar. Dengan kata lain, kita punya alasan yang jelas untuk beristirahat dan membatasi pekerjaan kita.
Kemalasan atau strategi kerja?
Saya berpandangan bahwa yang penting bukanlah seberapa keras kita bekerja, tetapi apakah suatu kegiatan efektif atau tidak dalam menggapai hal yang bernilai untuk kita[11].
Coba perhatikan skenario berikut yang sekilas terlihat malas, tapi sebenarnya merupakan strategi kerja.
- Kamu menolak tugas-tugas receh[12] agar memiliki waktu berpikir lebih mendalam,
- Kamu membatasi pekerjaan agar tidak kewalahan,
- Kamu berkata “tidak” untuk tugas di luar tanggung jawab agar terhindar[13] dari jebakan pemikiran makin sibuk makin sukses,
- Kamu membuat sistem otomatis untuk tugas berulang sehingga punya waktu untuk tugas kreatif.
Kecenderungan menghakimi orang lain dengan cap malas berakar dari glorifikasi kerja keras, jam kerja panjang, dan kesibukan terus-menerus. Yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan mengarah pada tujuan yang jelas serta menyadari bahwa kita masih memiliki keterbatasan.
Belajar membedakan perilaku malas dan manajemen pengaturan kerja akan sangat membantu. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa dengan yakin menolak tekanan untuk terus-menerus produktif—tanpa rasa bersalah.
Memiliki manajemen pengaturan kerja bukan berarti kita hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Memenuhi kewajiban kita pada rekan kerja, keluarga, dan komunitas tetap tak boleh dilupakan.
Namun, dengan batasan yang sehat, kita tak lagi terjebak dalam pandangan bahwa makin banyak yang dilakukan, makin baik.
Sebelum melabel seseorang sebagai pemalas, coba pikirkan juga apakah terdapat kemungkinan alasan yang masuk akal di balik tindakan mereka. Bisa jadi mereka memiliki cara tersendiri untuk mengatur energi agar bisa menghadapi tantangan yang tak bisa kita lihat atau memiliki prioritas yang berbeda.
Terkadang, bekerja lebih sedikit bukanlah kemalasan, tetapi justru bukti sebuah kebijaksanaan.
Kezia Kevina Harmoko berkontribusi dalam penerjemahan artikel ini.
References
- ^ Semakin banyak orang (inews.co.uk)
- ^ Am I Depressed or Lazy? (www.psychologytoday.com)
- ^ dianggap “anak emas” (www.theatlantic.com)
- ^ agama-agama yang dikenal luas (www.proquest.com)
- ^ mitos kerja yang berbahaya (www.psychologytoday.com)
- ^ etika kerja Protestan (www.vox.com)
- ^ kelelahan mental (theconversation.com)
- ^ penelitian (link.springer.com)
- ^ jarang mendapatkan promosi (www.frontiersin.org)
- ^ mengungkap (www.youtube.com)
- ^ hal yang bernilai untuk kita (blog.practicalethics.ox.ac.uk)
- ^ tugas-tugas receh (www.bbc.co.uk)
- ^ terhindar (theconversation.com)
- ^ Rachata Teyparsit/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Katrien Devolder, Director of Public Philosophy, Professor of Applied Ethics, University of Oxford