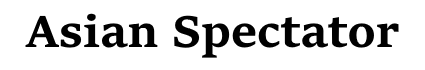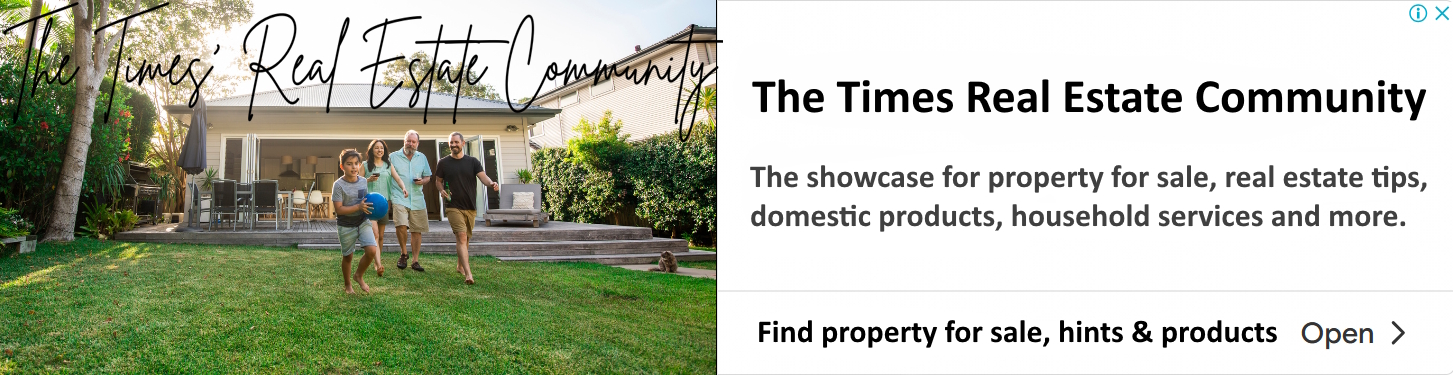_David_ vs _Goliath_: mengapa pendanaan PLTU di Indonesia lebih perkasa ketimbang energi terbarukan
- Written by Achmed Shahram Edianto, PhD Candidate, Tohoku University

Lebih dari 130 negara di dunia telah menyatakan komitmen dekarbonisasi[1], atau upaya mengurangi emisi gas rumah kaca domestik hingga ke titik nol emisi karbon (net zero). Salah satu langkahnya adalah menggenjot pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang minim emisi.
Sayangnya, komitmen ini tidak didukung kebijakan yang memadai. Sebanyak delapan negara – salah satunya Indonesia – masih menerima lebih banyak dana untuk proyek listrik berbasis energi fosil (khususnya batu bara) dibandingkan proyek energi terbarukan.
Temuan tersebut termuat dalam studi tim saya yang terbit pada Februari 2022 di jurnal Energy for Sustainable Development[2]. Kami menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proporsi aliran pembiayaan luar negeri ke proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di 23 negara, dibandingkan dengan energi terbarukan.
Riset kami fokus pada pembiayaan selama 2013-2017 yang bersumber dari institusi yang terafiliasi dengan negara investor (government-affiliated institutions), seperti China Development Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), Export-Import Bank of Korea (KEXIM), dan sebagainya.
Hasil studi menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak memiliki kebijakan yang kuat untuk mendukung energi terbarukan dan nilai ekonomi karbon, kemungkinan besar akan menerima lebih banyak pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Penelitian kami juga mengungkapkan adanya faktor lain yang memengaruhi fenomena ini, yaitu perjanjian bilateral yang justru mendorong pengembangan industri batu bara.
Lemahnya kebijakan pro energi terbarukan Indonesia
Riset kami memperlihatkan total pembiayaan luar negeri untuk PLTU di Indonesia mencapai US$ 17 Miliar (sekitar Rp 243 triliun). Sedangkan pembiayaan proyek listrik energi terbarukan hanya sebesar US$ 1 Miliar (Rp 14,3 triliun).
Ada tiga hal yang menyebabkan aliran pembiayaan ini begitu timpang.
1) Lemahnya dukungan kebijakan bagi energi terbarukan.
Niat pemerintah untuk menyediakan “listrik murah dan merata” demi mengimbangi pertumbuhan penduduk dan mencapai target pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, langkah ini menyebabkan pemerintah mengambil jalan pintas – memprioritaskan batu bara sebagai sumber utama pembangkitan listrik.
Pemerintah pun berupaya mengimbangi hal ini dengan menargetkan porsi energi terbarukan yang cukup ambisius dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN)[3], yaitu sebesar 23% dari total bauran pada tahun 2025. Sayangnya, target ini belum tercermin dalam kebijakan energi yang lebih memprioritaskan batu bara.
Tantangan berlanjut dengan regulasi[4] pemanfaatan energi terbarukan yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2017. Regulasi mengatur harga pembelian listrik energi terbarukan harus mengacu pada Biaya Pokok Produksi (BPP) pembangkitan listrik di suatu daerah.
Meski bertujuan untuk menstabilkan tarif listrik, aturan ini justru menyulitkan masuknya listrik energi terbarukan di daerah yang didominasi oleh “pembangkit murah” yakni PLTU. Pasalnya, biaya produksi listrik energi terbarukan secara ekonomi masih “lebih mahal”.
2) Minim kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK), misalnya berupa pajak karbon ataupun perdagangan karbon.
Saat studi ini dilakukan, ketiadaan kebijakan ini di Indonesia justru memberikan ruang besar bagi pengembangan industri dengan intensitas karbon yang tinggi. Contohnya adalah pembangkit berbasis energi fosil di sektor ketenagalistrikan.
Nihilnya kebijakan NEK membuat biaya lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan polusi udara tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi energi fosil.
Untungnya, pada akhir tahun lalu pemerintah sudah menerbitkan kebijakan NEK melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021[5]. Kita tinggal melihat bagaimana efektivitasnya terhadap sektor ketenagalistrikan.
3) Kesepakatan bilateral yang mendukung industri batubara, misalnya Pernyataan Bersama Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 2015.[6]
Melalui perjanjian ini, Jepang berkomitmen membantu pembangunan PLTU dengan efisiensi tinggi di Indonesia sebagai bagian dari ambisi yang lebih luas untuk menyokong proyek infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan pengiriman dan transportasi massal cepat.
Perjanjian ini juga menitikberatkan rencana Jepang untuk memanfaatkan dana publik demi membantu Indonesia mencapai program perluasan PLTU.
Yang perlu digarisbawahi adalah, perjanjian ini berasal dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari sisi Indonesia, perjanjian ini merupakan cerminan rencana pemerintah untuk membangun PLTU secara masif pada saat itu, melalui megaproyek listrik 35.000 Megawatt.[7]
Presidensi G20 sebagai momentum
Badan Energi Internasional (International Energy Agency, atau IEA) mencatat laju investasi PLTU terus menurun[8]. Beberapa investor pun mulai menarik diri dari proyek yang direncanakan. Tren ini dapat terus membaik karena adanya komitmen penghentian pembiayaan luar negeri untuk pembangunan PLTU[9] dari negara-negara investor yang diteken dalam konferensi iklim PBB (COP26) pada November silam.
Indonesia juga menjadikan COP26 sebagai momentum pertunjukan komitmen dan ambisi mencapai nol emisi karbon (net zero emission) pada 2060 mendatang atau bahkan lebih cepat[10]. Indonesia juga berkomitmen untuk mengakselerasi penghapusan penggunaan batu bara (coal phase-out) dalam sistem ketenagalistrikannya pada tahun 2040 dengan bantuan teknis dan finansial dari negara-negara maju.
Indonesia perlu menjaga momentum tersebut dalam presidensi G20 pada tahun 2022 ini. Dalam perhelatan ini, Indonesia memprioritaskan tiga isu utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital.
Sebagai negara penerima pembiayaan, Indonesia dapat berfokus pada penguatan kebijakan yang mendukung pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Harapannya, kebijakan tidak terpaku pada upaya pengurangan pembiayaan internasional untuk PLTU.
Saat ini pemerintah telah menyiapkan Strategi Besar Energi Nasional (GSEN)[11] yang mencakup rencana transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan diperkenalkan dalam pertemuan G20. Strategi ini, yang juga didukung regulasi NEK, diharapkan dapat memberikan sinyal positif terhadap dunia internasional.
Selain itu, Indonesia dapat mengajukan ide segar dan langkah konkret lain dalam pertemuan ini. Salah satunya adalah transparansi seluruh informasi pembiayaan[12] – bukan hanya pembiayaan publik, tapi juga swasta – di sektor batu bara dan energi terbarukan.
G20 dapat menjadi ajang untuk membuktikan bahwa Indonesia tengah membenahi kerangka kebijakan energinya secara lebih menyeluruh, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah target yang tepat bagi investasi di sektor energi terbarukan.
References
- ^ komitmen dekarbonisasi (www.un.org)
- ^ jurnal Energy for Sustainable Development (www.sciencedirect.com)
- ^ Kebijakan Energi Nasional (KEN) (jdih.esdm.go.id)
- ^ regulasi (jdih.esdm.go.id)
- ^ Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (peraturan.bpk.go.id)
- ^ Pernyataan Bersama Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 2015. (www.mofa.go.jp)
- ^ megaproyek listrik 35.000 Megawatt. (industri.kontan.co.id)
- ^ laju investasi PLTU terus menurun (www.iea.org)
- ^ komitmen penghentian pembiayaan luar negeri untuk pembangunan PLTU (unfccc.int)
- ^ nol emisi karbon (net zero emission) pada 2060 mendatang atau bahkan lebih cepat (unfccc.int)
- ^ Strategi Besar Energi Nasional (GSEN) (ebtke.esdm.go.id)
- ^ transparansi seluruh informasi pembiayaan (www.bu.edu)
Authors: Achmed Shahram Edianto, PhD Candidate, Tohoku University