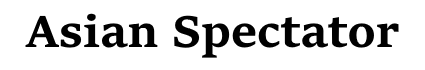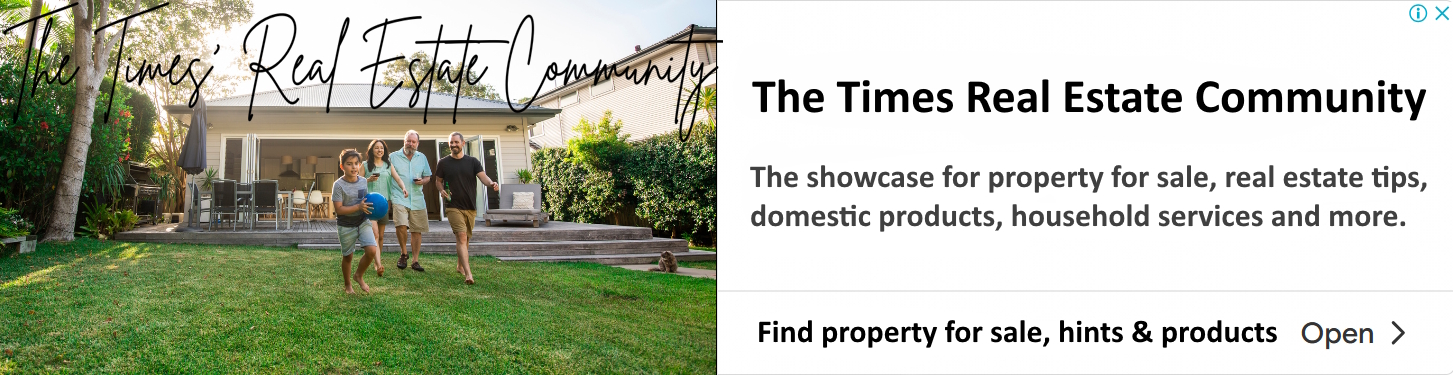Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi: Bagaimana pendekatan keadilan restoratif sangat merugikan korban kekerasan seksual
- Written by Marsha Maharani, Researcher, Indonesia Judicial Research Society

Pada 2019, seorang perempuan pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) diperkosa oleh empat pegawai laki-laki[1] yang salah satunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setahun berselang, pihak kepolisian justru menutup kasus ini setelah mengarahkan korban untuk menikah saja[2] dengan salah satu pelaku.
Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara kasus pidana dengan upaya perdamaian disebut sebagai upaya keadilan restoratif[3] (restorative justice).
Praktik menikahkan pelaku dengan korban dalam kasus pemerkosaan seringkali dianggap sebagai salah satu[4] bentuk keadilan restoratif. Polisi kemudian menghentikan perkara pidana karena mengganggap pihak korban dan pelaku sudah berdamai.
Nyatanya, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual di Indonesia justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan hak pemulihan atas apa yang dialaminya dan pelaku terbebas dari tanggung jawab hukuman pidana yang seharusnya ia terima.
Setidaknya ada beberapa alasan mengapa keadilan restoratif tidak layak diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual.
1. Merugikan korban, menguntungkan pelaku
Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender[5] oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menemukan bahwa hampir 60% responden yang pernah mengalami kekerasan seksual tidak memperoleh penyelesaian atas tindak pidana yang mereka alami. Sekitar 39,9% responden memperoleh penyelesaian dengan pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2% responden menikah dengan pelaku.
Fakta tersebut salah satunya dipicu oleh cara berpikir masyarakat yang masih membenarkan praktik menikahkan korban dengan pelaku sebagai win-win solution bagi kedua belah pihak.
Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, korban maupun keluarganya kerap kali bersedia dinikahkan dengan pelakunya karena ingin melepaskan diri[6] dari ketakutan dan perasaan malu atas tindak pidana yang menimpa mereka.
Hingga kini, banyak masyarakat yang masih membenarkan praktik bermasalah ini karena menganggap kekerasan seksual adalah aib[7] sehingga pernikahan dianggap dapat menutup aib korban dan keluarganya serta agar anak yang lahir akibat perkosaan tersebut dapat memiliki ayah.
Padahal, praktik tersebut justru sangat tidak adil bagi korban, namun menguntungkan pelaku. Survei[8] yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 menunjukkan bahwa 51,6% responden menganggap bahwa pernikahan antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku.
Situasi ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku adalah permasalahan sosial dari kasus pemerkosaan yang ternyata tidak bisa dibenahi oleh hukum dan peraturan semata. Penanganannya harus dibarengi dengan edukasi dan perubahan pola pikir.
2. Memaksakan perdamaian, mengabaikan hak korban
Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus sepenuhnya memahami bahwa mekanisme perdamaian pada perkara kekerasan seksual sangat sulit untuk diterapkan. Sebab, terdapat kondisi relasi kuasa yang kuat antara pelaku dan korban.
Pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban justru memberikan beban psikis[9] terhadap korban. Pasalnya, korban – yang sebagian besar adalah perempuan – justru dipaksa secara tidak langsung untuk memaafkan pelaku. Padahal, korban sudah mengalamai kejadian traumatis yang sangat merugikan, termasuk kerugian fisik, psikis, maupun finansial.
Pendekatan seperti ini, dengan kata lain, sangat berpihak pada pelaku dan dapat meningkatkan resiko terjadinya re-viktimisasi terhadap korban.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2019 juga pernah menjelaskan[10] bahwa implementasi pendekatan keadilan restoratif bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual.
Jika ingin menerapkan mekanisme keadilan restoratif, maka tujuan utamanya haruslah untuk membuat korban berdaya. Caranya bisa melalui pemberian akses keadilan yang memadai untuk korban, seperti bantuan hukum, pendampingan psikologis yang layak, dan akses terhadap rumah aman, bukan dengan memaksa korban untuk memaafkan dan berdamai, bahkan menikah, dengan pelaku.
Hal utama yang korban kekerasan seksual butuhkan adalah pemulihan fisik maupun psikisnya. Dengan melanggengkan dan menganggap normal praktik menikahkan korban dengan pelaku ini, kita telah merampas hak korban atas pemulihan diri dan rasa aman.
Kesimpulannya, praktik menikahkan korban dengan pelaku bukanlah bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut justru sangat bertolak belakang dengan upaya pemulihan untuk korban. Proses keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku, sebaiknya tidak diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, terutama pemerkosaan.
3. Inkonsistensi aturan hukum
Mekanisme keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana[11] (Perkapolri 6/2019). Dua tahun setelahnya, terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021[12] tentang Penangangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021).
Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak mengatur istilah perdamaian antara korban dan pelaku. Artinya, mekanisme yang diatur dalam Perkapolri 6/2019 dan Perpol 8/2021 tersebut tidak berlandaskan norma yang diatur dalam ketentuan KUHAP.
Begitupun dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018[13] tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Isinya menekankan bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa serta merta dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai.
Di sisi lain, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)[14] mengatur penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak – yang ditangani dengan UU No. 11 Tahun 2012[15] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kepolisian seharusnya memperbarui peraturan internalnya agar selaras dengan norma dalam UU TPKS. Misalnya dengan mengatur pengecualian penggunaan keadilan restoratif bagi tindak pidana kekerasan seksual.
Urgensi evaluasi aturan teknis penegakkan hukum
Apapun alasannya, penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual dengan mekanisme perdamaian maupun menikahkan korban dengan pelaku sangat tidak dapat dibenarkan dan akan selalu merugikan korban.
Jika korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan, akan makin banyak korban kekerasan seksual yang enggan menyelesaikan kasusnya melalui mekanisme penegakan hukum. Mereka akan menganggap hal itu sia-sia.
Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, perlu mengevaluasi ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual, serta merevisi peraturan teknis yang memperkuat perlindungan dan pemulihan kepada korban.
References
- ^ diperkosa oleh empat pegawai laki-laki (www.vice.com)
- ^ untuk menikah saja (www.konde.co)
- ^ keadilan restoratif (www.umy.ac.id)
- ^ salah satu (www.umy.ac.id)
- ^ Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender (ijrs.or.id)
- ^ ingin melepaskan diri (news.detik.com)
- ^ kekerasan seksual adalah aib (theconversation.com)
- ^ Survei (mappifhui.org)
- ^ memberikan beban psikis (papers.ssrn.com)
- ^ menjelaskan (icjr.or.id)
- ^ Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (www.peraturanpolri.com)
- ^ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 (www.peraturanpolri.com)
- ^ Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 (erepository.uwks.ac.id)
- ^ UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (peraturan.bpk.go.id)
- ^ UU No. 11 Tahun 2012 (peraturan.bpk.go.id)
Authors: Marsha Maharani, Researcher, Indonesia Judicial Research Society