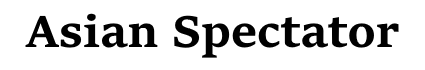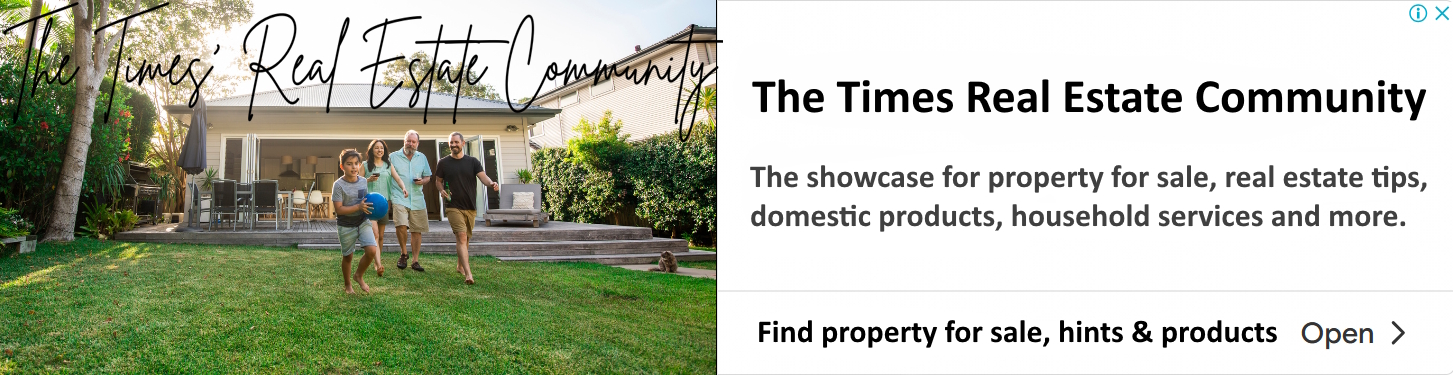Komunikasi ‘tone-deaf’ pemerintah: Kritik dianggap ancaman, dialog dibalas candaan
- Written by Benyamin Imanuel Silalahi, Peneliti, Universitas Gadjah Mada

● Petinggi negara, bahkan Presiden Prabowo Subianto, kerap melontarkan pernyataan yang bersifat tone deaf terhadap situasi sosial.
● Sikap tone-deaf memiliki kecenderungan apatisme dan erat dengan sikap represif.
● Pemerintah bisa memperbaiki komunikasi dengan publik melalui pendekatan psychological first aid.
Istilah tone-deaf[1] jika merujuk pada kamus Merriam-Webster dapat didefinisikan sebagai sikap yang menunjukkan ketidakpekaan atau ketidakpedulian terhadap perasaan individu/pihak lain, situasi emosional, atau norma sosial yang berlaku.
Dalam konteks bernegara, pemerintah yang tone deaf seolah-olah menganggap aspirasi publik penting untuk didengar, namun tidak mempedulikannya.
Inilah situasi yang tengah terjadi di Indonesia. Di tengah kecemasan publik, yang terdengar bukan empati, melainkan candaan tak pada tempatnya[2].
Salah satu contoh nyata tone-deaf pejabat pemerintah adalah pernyataan Hasan Nasbi[3], Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Alih-alih menunjukkan empati dan mengecam tindakan intimidatif tersebut, Hasan justru menanggapi dengan candaan, mengatakan, “Dimasak saja lah,” untuk kepala babi tersebut. Tentu saja, pernyataan ini menuai kritik dari begitu banyak kalangan.
Ada banyak pernyataan lainnya dari petinggi negara yang berbau tone-deaf. Mulai dari istilah “ndasmu[4]” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto, “kampungan[5]” oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntakntak, dan perumpamaan “anjing menggonggong[6]” oleh Prabowo yg merujuk pada pengkritiknya, hingga kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengomentari gizi pemain tim nasional (timnas) tidak bagus sehingga sulit menang[7].
Ketika suara rakyat menuntut kejelasan, yang muncul justru sikap meremehkan.
Pemerintah harus belajar bagaimana merespons publik dengan lebih baik dan empatik, terutama di saat krisis. Selayaknya konseling, langkah pertama bukan dengan membantah apa yang dirasakan masyarakat, tetapi mendengarkan, lalu hadir dan mengakui.
‘Tone-deafness’ bukan sekedar miskomunikasi
Jika dibiarkan, tone-deafness bisa menjadi indikator keretakan hubungan emosional dan psikologis antara negara dan warganya. Sebab, salah satu aspek penting[8] dalam komunikasi pemerintahan yang efektif, khususnya di tengah krisis, adalah kemampuan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan spesifik dari audiens.
Meskipun miskomunikasi adalah bagian dari masalah, tone-deafness lebih dari sekadar kesalahan dalam penyampaian informasi. Pemerintah yang tone deaf artinya telah gagal secara sistematis untuk mendengarkan suara masyarakat dan merespons dengan cara yang sesuai. Masalah ini juga mencerminkan ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian terhadap emosi masyarakat.
Tone deaf tidak hanya terjadi ketika pemerintah melakukan respons langsung pada kritik. Sebagai contoh, di tengah polemik revisi UU TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah konten AI[10] yang tidak relevan dengan keresahan publik. Netizen segera bereaksi, menyebutnya sebagai “Wapres tone-deaf”.
Dalam konteks ini, Gibran menunjukkan sikap tone deaf, bukan karena ia merespons kritik dengan candaan maupun karena salah bicara, tetapi karena ia gagal membaca situasi publik yang sedang genting. Sikapnya seolah negara ini baik-baik saja.
Respons semacam ini memperlihatkan ketimpangan empati antara penguasa dan rakyat. Padahal, komunikasi publik tidak hanya dituntut informatif, tetapi juga harus mampu menangkap dan merespons realitas psikologis masyarakat. Empati[11] menjadi salah satu nilai fundamental dalam komunikasi publik, khususnya bagi pelayan publik.
Apatisme dan kecenderungan represif
Sikap tone-deaf sering datang bersama dua hal: apatisme[12] dan kecenderungan represif. Apatisme ini erat dengan sikap represif[13]. Sementara represi terhadap kritikan[14] merupakan salah satu dari pilar-pilar utama yang digunakan rezim otoriter untuk mempertahankan stabilitas dan kekuasaan.
Pernyataan yang bersifat tone deaf seakan menunjukkan bahwa suatu kejadian bukanlah hal penting. Celetukan Hasan soal teror kepala babi, contohnya, seakan ingin menegaskan bahwa ada rasa aman yang dipaksakan. Padahal, ucapannya tersebut justru menyakitkan bagi publik, bukan karena bahasanya, tetapi karena publik merasa tidak aman.
Tone deaf juga dapat membuka pintu terjadinya represi terhadap rakyat oleh negara. Represi tidak selalu bersifat brutal, tetapi juga dapat berbentuk soft-repression[15], yaitu pembatasan ruang kritik secara simbolik dan kultural. Dalam konteks ini, komunikasi tone-deaf menjadi strategi tidak langsung untuk mengontrol narasi, menghindari konfrontasi langsung, dan menstabilkan kekuasaan dengan cara melemahkan legitimasi kritik.
Alih-alih membuka ruang diskusi, nada bicara yang sumbang justru menyingkirkan suara rakyat secara perlahan. Dalam jangka panjang, ini bisa sama merusaknya dengan represi formal, karena masyarakat merasa tak punya tempat untuk menyuarakan kekecewaan mereka secara sehat dan terbuka.
Akibatnya, rakyat merasa diabaikan, bahkan dianggap tidak layak didengar.
Cara menangani rakyat yang terluka: Panduan untuk pemerintah
Untuk merespons publik yang kecewa, pemerintah harus belajar satu hal penting: bersikap seperti seseorang yang tahu bagaimana menghadapi orang yang sedang terluka. Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah tidak membantah perasaan rakyat. Kemudian, pemerintah bisa mendengarkan, sehingga rakyat dapat merasakan kehadirannya.
Salah satu pendekatan yang relevan yang bisa menjadi panduan bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi dengan publik adalah psychological first aid[16]. Pertolongan pertama ini terdiri dari tiga prinsip utama.
Pertama adalah mengamati (look). Amati lingkungan serta kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis. Kalau perlu, pahami luka dalam bahasa generasi saat ini yang menyuarakannya. Harus muncul pemahaman yang jelas terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Contohnya, saat publik menunjukkan keresahan terhadap revisi UU TNI, pemerintah bisa mengamati tagar-tagar yang muncul dari warganet di dunia maya, lalu menyelenggarakan diskusi publik di ruang-ruang daring. Ini bisa menjadi dasar penyusunan respons yang peka.
Kedua, pemerintah perlu mendengar (listen). Mendekati masyarakat dengan membangun hubungan dan mendengarkan secara aktif untuk memahami perasaan serta kebutuhan mereka.
Pemerintah bisa mengadakan forum dialog terbuka atau konsultasi publik daring, sehingga masyarakat bisa menyampaikan kritik terhadap kebijakan. Seperti saat menyusun UU baru, pemerintah bisa mengadakan live discussion yang benar-benar ditanggapi, bukan sekadar formalitas. Atau, pemerintah bisa mengundang perwakilan-perwakilan dari kelompok masyarakat yang menyuarakan keresahan untuk berdialog.
Ketiga, penting untuk bisa menghubungkan (link). Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi permasalahan dengan menghubungkan mereka kepada sumber daya atau dukungan yang diperlukan.
Dalam kasus pengiriman kepala babi kepada kantor Tempo, pemerintah bisa menghubungkan Tempo dengan proteksi dan penegakan hukum pemerintah secara langsung. Selain itu, pemerintah juga bisa mengedukasi publik tentang kebebasan pers dan bagaimana hak tersebut dijamin oleh negara.
Penerapan prinsip-prinsip ini dalam komunikasi publik dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dalam merespons kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Dengan mengamati situasi secara cermat, mendengarkan aspirasi publik secara aktif, dan menghubungkan mereka dengan solusi yang tepat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan warga negara.
Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konseling ini ke dalam strategi komunikasi, pemerintah dapat menunjukkan empati yang tulus dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik.
Pemerintah harus sadar, komunikasi bukan alat untuk mengendalikan narasi, tetapi jembatan membangun relasi. Relasi bisa rusak bukan karena kebijakan yang salah, melainkan karena cara bicara yang tak lagi menyentuh rasa. Kalau negara ingin didengar, ia harus terlebih dulu belajar mendengar.
References
- ^ tone-deaf (www.merriam-webster.com)
- ^ candaan tak pada tempatnya (www.kompas.id)
- ^ pernyataan Hasan Nasbi (megapolitan.kompas.com)
- ^ ndasmu (www.bbc.com)
- ^ kampungan (www.tempo.co)
- ^ anjing menggonggong (nasional.kompas.com)
- ^ gizi pemain tim nasional (timnas) tidak bagus sehingga sulit menang (news.detik.com)
- ^ aspek penting (doi.org)
- ^ Reca Ence AR/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah konten AI (www.suara.com)
- ^ Empati (doi.org)
- ^ apatisme (dergipark.org.tr)
- ^ represif (doi.org)
- ^ represi terhadap kritikan (doi.org)
- ^ soft-repression (doi.org)
- ^ psychological first aid (cpmh.psikologi.ugm.ac.id)
- ^ Donny Hery/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Benyamin Imanuel Silalahi, Peneliti, Universitas Gadjah Mada