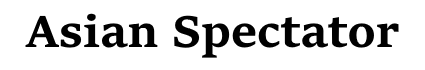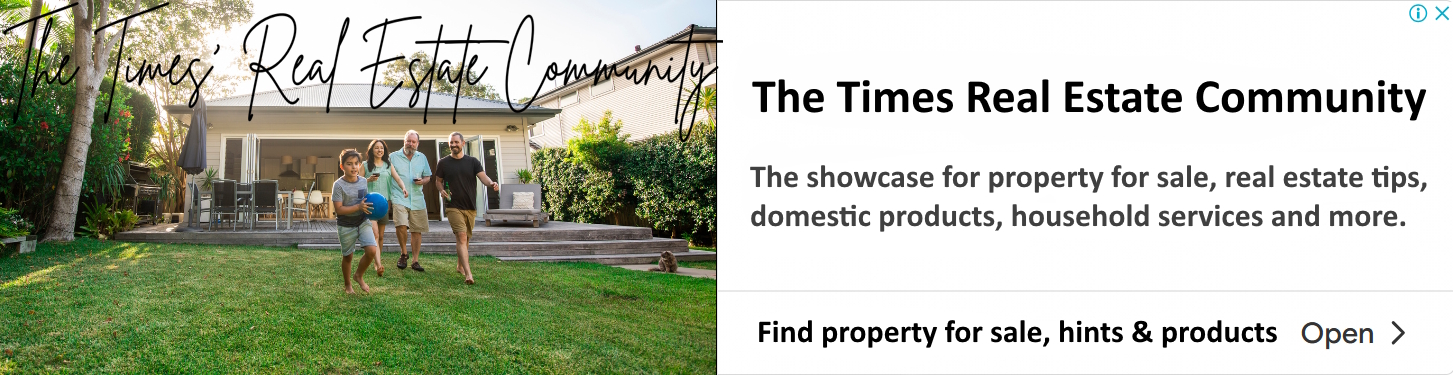Bagaimana cara berbahagia dengan yang kita miliki dan berhenti membandingkan diri
- Written by Joshua Forstenzer, Senior Lecturer in Philosophy and Co-Director of the Centre for Engaged Philosophy, University of Sheffield

Kadang-kadang, kita merasa tak seharusnya bahagia dengan apa yang kita miliki. Apalagi kita hidup di dunia yang penuh ketidakadilan dan kekejaman di berbagai lapisan lingkungan kita.
Bukan cuma itu, beberapa orang terdekat yang saya kenal juga merupakan sosok yang denial: teguh menolak hal yang sulit diubah.
Kita pun hidup di tengah sistem ekonomi yang mengambil keuntungan dari perasaan pribadi seperti merasa kurang (insecure), menginginkan sesuatu, dorongan membandingkan diri dengan orang lain, dan rasa iri.
Perasaan iri kerap membuat kita merasa kurang dan menginginkan sesuatu, bukan kebalikannya. Ini terjadi berkat kepiawaian iklan: memunculkan kebutuhan yang “dipersepsikan[1]” alias kebutuhan semu. Kita melihat seseorang yang hidupnya “ideal"—seru, seksi, kreatif, kemudian menginginkan apa yang mereka miliki: sepatu, jam tangan, liburan, atau apa pun itu.
Perasaan iri tak akan muncul tanpa adanya perbandingan. Sementara perbandingan memerlukan standar pengukuran untuk mengukur diri kita.
Kultur pop menawarkan beberapa standar. Mulai dari seberapa menarik kita sebagai objek seksual (jumlah match di aplikasi kencan) atau seberapa eksis kita di dunia digital (jumlah pengikut atau likes). Semua ukuran ini memengaruhi konsep kesuksesan atau kegagalan kita.
Efek negatif ‘standar palsu’
Terkadang, standar-standar tersebut menjadi ukuran kesuksesan palsu.
Pikirkanlah salah satu contoh, misalnya seorang "pria yang punya high-value”. Di internet, sosok tersebut sama dengan pria yang banyak uang, pertemanan luas, dan berguna bagi banyak orang[2].
Ujung-ujungnya, definisi itu mendorong individu mengejar capaian materi dan peningkatan diri yang palsu untuk mencapai kesuksesan atau daya tarik seksual. Lagu TikTok yang viral, I’m Looking for a Man in Finance[3], cukup menggambarkan standar tersebut.
Asumsi tersembunyi di standar ini adalah: semakin banyak “hal keren” yang kita miliki, semakin bernilai pula kita sebagai individu. Di balik asumsi tersebut terdapat konsep terselubung: kita hanya bisa “memiliki” sesuatu yang bernilai dalam hidup—alih-alih menjadi sesuatu yang bernilai[4].
Asumsi ini biasanya berakar dari perasaan tak pantas (shame): perasaan bahwa diri kita saja tidaklah cukup. Kita seakan-akan tak layak untuk menentukan standar kesuksesan atau kegagalan dalam hidup kita sendiri.
Merasa malu dengan diri sendiri sebenarnya tak melulu buruk. Perasaan negatif yang sehat membuat kita sadar ketika membuat kesalahan atau melakukan tindakan yang tak sesuai dengan standar moral kita sendiri. Perasaan rendah diri ini mengingatkan kita untuk melakukan perubahan.
Rasa tak pantas yang menyakitkan
Versi yang tak sehat dari rasa malu adalah perasaan tak pantas. Perasaan ini lebih dalam dari sekadar malu atau keraguan moral. Peneliti sifat rentan (vulnerability) Brené Brown[6] mendefinisikannya sebagai “perasaan menyakitkan yang intens atau keyakinan bahwa diri kita penuh kekurangan sehingga tak layak mendapatkan cinta”.
Perasaan tak pantas itu benar-benar mencengkeram[7] sehingga bisa membuat kita melakukan apa saja agar tak menyadari kehadiran perasaan tersebut.
Sikap denial tersebut dapat terbentuk saat kita mendengar suara hati (akibat pengalaman pahit masa lalu) yang seakan-akan menjadi nyata karena kita membandingkannya dengan sekitar kita.
Suara yang begitu menghakimi itu kemudian memberi tahu bahwa kita bukan sedang mengalami suatu kegagalan, tapi kita adalah orang gagal. Konsep ini sering disebut “proyeksi[8]”.
Di sisi lain, meski kita menyadari perasaan tak pantas itu, tak jarang kita malah bernegosiasi dengannya. Kita mengupayakan perbaikan ke lingkungan sekitar kita, sebagai penebusan akan perasaan tak berharga yang kita alami.
Di masa yang lebih kelam, perasaan tak pantas ini bisa mengambil alih kehidupan kita, membuat kita merasa tak berdaya, dan mendorong kita menjauhi setiap relasi yang ada.
Cara melawan perasaan tak pantas dan bahagia dengan diri sendiri
Perasaan tak pantas bisa jadi sangat sulit untuk kita hadapi. Mengenali dan berefleksi terkait perasaan tersebut bisa menjadi langkah yang bermanfaat. Mengubah cara memahami diri dan hubungan kita dengan orang lain juga dapat membantu.
Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Namun, agar lebih mudah dijelaskan, ada tiga pilihan yang cukup berkesan menurut saya.
1. Stoikisme
Stoikisme[9] (stoicism) merupakan sebuah aliran filsafat yang intinya meyakini bahwa sifat bawaan kita seharusnya menjadi pribadi yang stabil. Oleh karena itu, tujuan dari hidup kita seharusnya adalah memenuhi kestabilan tersebut serta mengembangkan diri.
Sering kali kita menilai diri berdasarkan keadaan imajiner (“kalau saya lebih kurus, lebih bagus”) dan kepercayaan bahwa tindakan tertentu akan membuat imajinasi tersebut jadi nyata (“diet cokelat akan mengembalikan bentuk tubuh saya seperti saat remaja”).
Kedua hal tersebut bisa menyesatkan. Sebab, hal-hal yang kita inginkan bisa berdampak buruk untuk diri kita. Kita pun tak bisa mengendalikan masa depan seperti yang kita bayangkan.
Para Stoik berpendapat bahwa seseorang harus menyelaraskan kondisi emosionalnya dengan hal-hal yang mereka kejar. Agar bisa berkembang, kita juga perlu terus-menerus mengendalikan diri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan stoikisme mendorong kita untuk mengenali dan mengembangkan kebiasaan yang mendorong kita dekat dengan lingkungan dan dunia secara lebih luas. Ini dimulai dari diri kita sendiri, lalu keluarga, komunitas, negara, kemanusiaan secara luas dan bahkan alam semesta.
2. Eksistensialisme
Berkebalikan dengan stoikisme, eksistensialisme justru percaya bahwa tak ada tujuan hidup hakiki dalam hidup manusia[11]. Tak ada hal apa pun yang bisa mendefinisikan diri kita. Kita memiliki sesuatu yang tak bisa diambil oleh siapa pun: kapasitas mengubah diri, menyambut hal baru, hingga memulai gebrakan unik.
Perasaan hampa yang terkadang muncul setelah menggapai target yang lama diimpikan (misalnya mendapat promosi jabatan yang signifikan) bisa terasa membingungkan. Namun, perasaan inilah yang menjadi pengingat bahwa tak ada yang membatasi kita untuk mencapai satu tujuan saja. Semuanya bergantung pada diri kita sendiri.
Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita merupakan individu yang bebas sehingga kita juga bertanggung jawab untuk hal-hal yang kita lakukan dan makna yang kita berikan pada hal tersebut.
3. Psikoterapi humanistik
Perspektif psikoterapi humanistik[13] menawarkan jalan tengah dari dua pandangan sebelumnya. Pandangan ini mengajak kita memandang diri dengan cinta kasih. Sebab, kita adalah individu yang kompleks dan penuh tanggung jawab, sekaligus tak sempurna dan penuh kerentanan. Kita pun selalu berada dalam hubungan yang terus berkembang sehingga memberi kita makna dan tujuan hidup.
Dalam pendekatan ini, baik hubungan yang kita jalin maupun perhatian yang kita berikan dan terima akan menjawab pertanyaan hidup terpenting: “Siapa kita?"—terutama saat kita mengalami krisis. Menjawab pertanyaan itu akan membutuhkan ketulusan, kebaikan, serta kejujuran kita dalam menjalin hubungan apa pun.
Dengan begitu, kita melihat diri sendiri dan orang lain bukan sekadar individu dengan kelemahan, tetapi sosok unik yang terus berkembang.
References
- ^ dipersepsikan (theconversation.com)
- ^ banyak uang, pertemanan luas, dan berguna bagi banyak orang (knowyourmeme.com)
- ^ I’m Looking for a Man in Finance (www.youtube.com)
- ^ menjadi sesuatu yang bernilai (www.nytimes.com)
- ^ Alphavector/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Brené Brown (brenebrown.com)
- ^ benar-benar mencengkeram (cptsdfoundation.org)
- ^ proyeksi (www.ncbi.nlm.nih.gov)
- ^ Stoikisme (theconversation.com)
- ^ Alphavector/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ tak ada tujuan hidup hakiki dalam hidup manusia (www.jstor.org)
- ^ Alphavector/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Perspektif psikoterapi humanistik (www.psychologytoday.com)
- ^ Alphavector/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Joshua Forstenzer, Senior Lecturer in Philosophy and Co-Director of the Centre for Engaged Philosophy, University of Sheffield