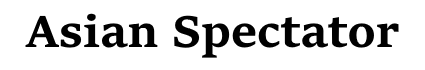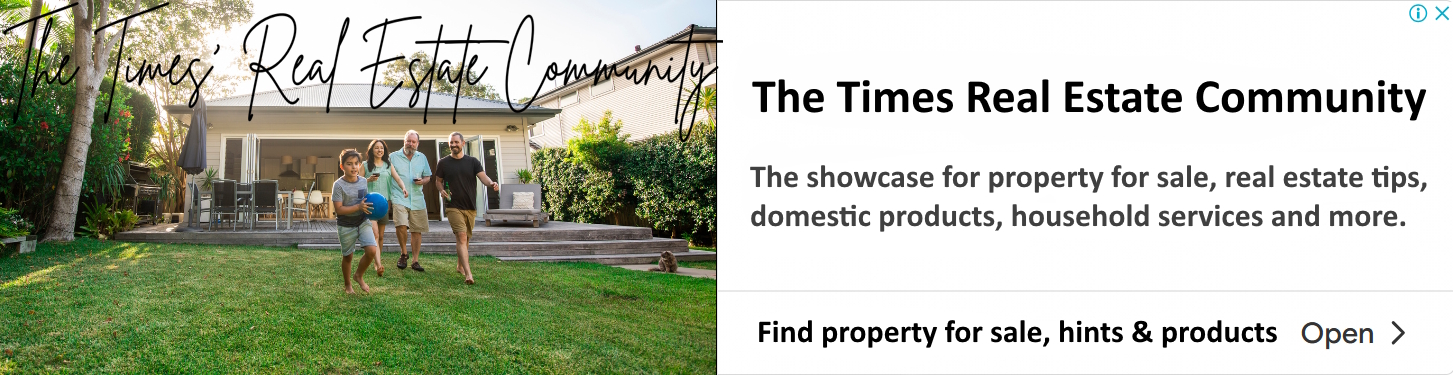Sadarkah kita bahwa program makanan gratis adalah alat kontrol pemerintah terhadap rakyat?
- Written by Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro

● Alih-alih menyejahterakan rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga membuat rakyat ketergantungan terhadap kemurahan hati negara
● Program MBG merupakan contoh konkret dari strategi kapitalisme neofeodal
● Publik harus memperkuat analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah dan membangun gerakan sosial yang lebih luas
Sudah tiga bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Masih banyak pro-kontra dalam penerapan program populis yang menyasar lebih dari 82 juta penerima ini.
Di luar tujuannya dalam membantu mencukupi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, disadari atau tidak, program MBG[1] merupakan langkah asistensialisme pemerintah terhadap rakyat.
Konsep asistentialisme[2] merujuk pada strategi pemerintah yang memberikan bantuan langsung (seperti makanan gratis atau subsidi tertentu) kepada kelompok miskin. Namun, strategi ini belum tentu bisa mengatasi akar penyebab struktural dari kemiskinan itu sendiri.
Sering kali tujuan politik asistensialisme adalah untuk mempertahankan dukungan sosial tanpa perlu menyentuh akar struktural kemiskinan[3]. Secara tidak langsung, pemerintah menggunakan program MBG sebagai alat kontrol sosial untuk memperkuat ketergantungan kelas bawah terhadap negara.
Pemerintah melanggengkan kemiskinan
Masifnya program-program bantuan pemerintah yang bersifat populis menjadikan Indonesia contoh nyata dari model kapitalisme neofeodal[4], yaitu model ekonomi-politik ketika dinamika kapitalistis[5] berpadu dengan struktur kekuasaan oligarkis[6].
Kapitalisme neofeodal berbeda dengan teori kapitalisme liberal[7] yang menjunjung persaingan dan meritokrasi (pemberian kesempatan terhadap individu berdasarkan kemampuan dan prestasi). Dalam kapitalisme neofeodal, ekonomi dan sumber daya negara dikontrol secara sistemik oleh segelintir elite.
Sumber daya publik dikelola guna menguntungkan elite, sementara kelas-kelas subordinat dipertahankan dalam kondisi ketergantungan struktural.
Pada akhirnya, negara tidak berfungsi sebagai entitas netral dalam mengatur ekonomi, melainkan sebagai alat yang melanggengkan ketimpangan. Prabowo dan para elite politik lainnya seolah berperan sebagai penjamin reproduksi kapital, padahal sumber daya negara hanya berputar di tangan segelintir elite.
Setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto, bukannya terjadi demokratisasi yang substansial, justru terbentuk struktur kekuasaan oligarkis yang lebih kompleks, yaitu yang berisi keluarga-keluarga konglomerat dan dinasti politik. Mereka seakan menyatukan kekuatan untuk mengontrol negara demi melanggengkan hegemoni mereka.
Program MBG merupakan salah satu manifestasi konkret dari strategi kapitalisme neofeodal ini. Meski dipromosikan sebagai upaya mengatasi ketahanan pangan, pada kenyataannya program dibiayai melalui realokasi anggaran dari sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Artinya, kebijakan sosial semacam ini bukanlah mekanisme redistribusi, melainkan alat kontrol sosial.
Alih-alih mengurangi ketimpangan, program seperti MBG justru memperkuat ketergantungan kelas bawah terhadap negara dan para elite ekonomi-politik yang mendominasi pemerintahan.
Melalui retorika populis yang mengusung kesejahteraan rakyat, Prabowo sebagai elite berupaya melegitimasi kebijakan MBG yang pada dasarnya bertujuan memperkokoh dominasi mereka.
Melalui retorika semacam ini, pemerintah berupaya menyembunyikan fakta bahwa ketimpangan bersifat struktural, bukan akibat kelangkaan sumber daya, apalagi kekurangan anggaran.
Melanggengkan kesadaran palsu
Karl Marx mendefinisikan kesadaran palsu (false consciousness[9]) sebagai ketidakmampuan kelas pekerja untuk mengenali kondisi eksploitasi mereka akibat dominasi ideologi kapitalis para borjuis. Ideologi kapitalis menampilkan sistem produksi yang ada sebagai sesuatu yang wajar dan tak terhindarkan—melalui institusi negara, media, dan budaya.
Di Indonesia, hal ini tercermin dalam narasi bahwa peningkatan kesejahteraan bergantung sepenuhnya pada kerja keras individu—yang pada gilirannya menutupi hambatan struktural dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.
Dalam konteks ini, program MBG menjadi instrumen penyebaran kesadaran palsu. Penyajiannya sebagai kebijakan yang menguntungkan rakyat miskin memperkuat ilusi bahwa kesejahteraan bergantung pada kemurahan hati negara, bukan pada perubahan struktural ekonomi.
Pada saat yang sama, pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar gas atau elpiji—yang menyebabkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Negara juga memangkas anggaran pendidikan–langkah yang berpotensi membatasi pengembangan kesadaran kritis di kalangan generasi muda. Pendidikan publik—yang seharusnya menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan—justru dilemahkan. Sementara kondisi ekonomi yang kian rentan dinormalisasi sebagai sesuatu yang tak terelakkan.
Dampak dari kebijakan ini semakin terasa di kalangan perempuan dan komunitas adat—terutama masyarakat Papua—yang mengalami marginalisasi berlapis dan sering kali diabaikan negara.
Secara garis besar, kebijakan pemerintahan Prabowo mencerminkan pola kapitalisme neofeudal. Pemerintah tampak sedang mempertahankan ketimpangan, alih-alih menguranginya.
Program seperti MBG, pada dasarnya tidak efektif untuk memberdayakan rakyat, melainkan hanya memperdalam ketergantungan terhadap negara dan elite ekonomi yang mengendalikannya.
Perlunya resistensi kolektif
Agar tidak terjebak dalam kesadaran palsu, rakyat harus memperkuat analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah serta membangun gerakan sosial yang lebih luas. Hal ini salah satunya terlihat melalui rangkaian aksi protes mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan mulai berkembangnya kesadaran politik kritis.
Hanya dengan kesadaran kolektif dan aksi bersama, jalan menuju transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis dapat diwujudkan. Melalui penciptaan ruang politik yang kolektif dan solidaritas sosial, siklus ketidakadilan dapat dipatahkan dan transisi menuju sistem yang lebih adil, egaliter, dan berkelanjutan dapat diwujudkan.
References
- ^ program MBG (ugm.ac.id)
- ^ asistentialisme (www.oecd.org)
- ^ kemiskinan (www.sciencedirect.com)
- ^ kapitalisme neofeodal (lareviewofbooks.org)
- ^ kapitalistis (kbbi.web.id)
- ^ oligarkis (kbbi.web.id)
- ^ liberal (www.networkideas.org)
- ^ misan nain/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ false consciousness (www.jstor.org)
- ^ Tabah Zaman/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro